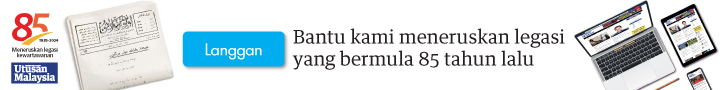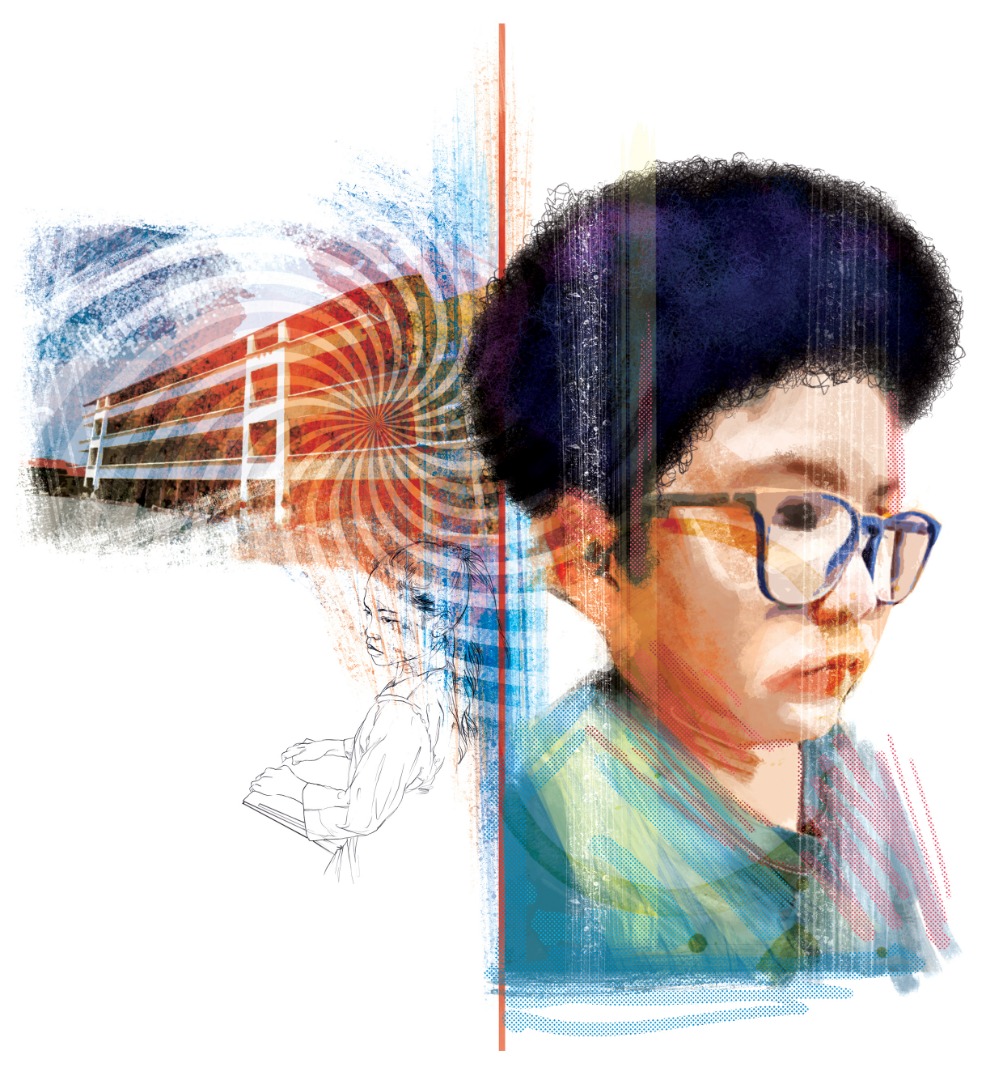Cerpen karya Zulaikha Adam
Lembar kalendar dikoyak lagi. Diremukkan dan dicampak ke dalam sebuah bakul sampah kecil di sisi meja belajar. Disember sudah habis dalam tidak sedar. Kini, Januari beraksi pula. Kotak-kotak yang terisi nombor disebut tarikh seakan tidak mahu berhenti daripada saling bergantian. Adib merenung peta dunia yang ditampal pada dinding berhadapan meja belajarnya. Dia memandang ke titik negara Eropah dan mengimbau ingatannya terhadap sebuah obelisk di Paris yang pernah dilihatnya di kaca TV.
Pada waktu-waktu begini, apakah yang sedang dilakukan oleh rakan seusianya? Sekolah bilakah dibuka semula, meskipun negara masih belum reda melawan wabak Covid-19. Bagaimanakah sesi persekolahan tahun ini di saat wabak yang berbentuk zarah masih merebak di mana-mana? Pada bekas pensel kainnya, tergantung rantai kunci Menara Eiffel pemberian Bahri teman rapatnya. Bahri berasal daripada keluarga berada. Kedua ibu-bapanya ialah peguam profilik tanah air. Jadi, tidak mustahil dia mampu beberapa kali terbang ke negara asing.
Namun, itu bukan perkara penting buat Adib kerana mengembara bukanlah cita-citanya, tetapi impian terbesarnya adalah untuk membina bangunan seperti Menara Eiffel. Filem Skyscraper seakan terbentang di hamparan peta di hadapannya. Bangunan itu tersangat tinggi, namun tidak mustahil bangunan setinggi itu mampu manusia cipta dengan tangan mereka. Sedangkan Jeddah Tower sedang dibangunkan bagi menyaingi Burj Khalifa yang mendapat gelaran bangunan tertinggi di dunia. Sudah tentu, manusia mencipta bangunan yang tinggi-tinggi bukan untuk mencari jalan menemukan Tuhan, sebaliknya untuk berbangga-bangga.
“Tuliskan cita-cita kamu atas kertas dan gulungkan kertas itu. Kemudian, masukkan ke dalam balang kaca ini. Balang kaca ini akan sentiasa berada di atas meja guru dan apabila kamu lihat balang kaca ini, seperti itu jualah kamu harus melihat cita-cita kamu.”
Adib menulis perkataan ‘ARKITEK’ dengan huruf besar kesemuanya. Dia menggulung kertas impian itu dan memasukkan ke dalam balang lutsinar itu tadi. Cikgu Solehah selalu mengingatkan dia tentang cita-cita dan cita-cita itu adalah kermurnian yang harus diperjuangkan. Tanpa dapat dikawal lagi, air matanya merembes. Peta dunia di hadapannya berubah kosong. Seluruh negara dan benua yang berada di hamparan peta itu lesap. Tinggal seakan laut yang terbentang kosong tanpa ombak. Tinggal warna biru pada lautnya sahaja.
“Tahun depan dah naik tingkatan lima. Kau jangan selalu ponteng pula. Sudahlah tahun ni merah saja nama kau dalam rekod kehadiran.” Bahri melayangkan pesanan ringkas dan Adib tidak pasti mahu mentafsirkan kata-kata Bahri itu sebagai nasihat atau sindiran.
Pesanan ringkas itu tidak dibalas. Sementara Adib mencapai hydrocortisone yang terkandung steroid dari dalam laci. Ubat itu dilumurkan ke seluruh badannya sehingga mengeluarkan bau kurang senang. Adik lelakinya berpusing-pusing ke kiri berbalas ke kanan. Terlalu resah untuk menidurkan diri. Adib sedar, tempaus itu telah menggelisahkan adik lelakinya malahan sesiapa saja yang berada dalam lingkungannya. Dan itulah juga punca mengapa dia tidak suka apabila Bahri mempersoalkan tentang persekolahannya.
Tidak sanggup melihat adik lelakinya terus kegelisahan, Adib keluar daripada ruang pengap itu. Di ruang tamu, ayahnya sedang menatap skrin tablet.
“Oh, belum tidur lagi?”
Adib hanya menyambut persoalan ringkas itu dengan gelengan.
“Sudah sapu ubat?”
Adib mengangguk pula.
“Abi sudah buat temujanji untuk kamu di Klinik Khizan di bandar Kuantan. Hari Ahad ini kita ke sana.”
“Ubat yang lama belum habis lagi, Abi.” Adib dengan halus cuba menolak ajakan itu. Dia sudah semakin malas untuk berjumpa mana-mana doktor atau ahli dermatologi.
“Demi kebaikan kamu juga.” Ayahnya merenung mata Adib berharap agar anak sulungnya itu tidak membantah.
“Dah 12 tahun Abi. Adib dah letih. Betul-betul letih.” Adib tidak membalas renungan ayahnya dan dengan segera dia meminta diri masuk ke bilik semula meninggalkan ayahnya dengan suara yang terlekat pada kerongkong.
Pagi ini ruang tamu berbunyi kecoh. Adib mengeringkan rambut alfronya sesudah mandi. Seperti kelaziman dia membungkus tubuhnya dengan baju berlengan panjang, kali ini berbelang-belang kuning coklat. Semalam, dia menzalimi dirinya sendiri padahal dia tahu alergik akan menyerangnya bila-bila masa jika dia berdegil memakan makanan laut. Tetapi, dia tidak dapat menolak nafsu jika Mak Langnya datang dari kampung, bermalam di ruamahnya dan memasakkan dia sekeluarga lauk-lauk luar biasa sedapnya.
“Dah berbelas tahun kau bawa budak tu ke hulur-kehilir. Sudah-sudahlah tu, Ngah. Cubalah rawatan kampung pula. Daun-daun herba, akar kayu, rempah ratus, pokok-pokok di hutan itu semua ada khasiatnya. Kau tak baca Kitab Tib? Kitab perubatan Melayu dulu-dulu. Penuh ilmu dalam tu, Ngah. Atas kau saja.”
“Aku dah mati kutu, Lang. Aku pernah bawa sekali jumpa ustaz sebab ada kawan aku kata anak aku ni kena buatan orang. Ustaz itu pun mengiayakan saja. Dah bergelen air ayat suci aku mandikan dia. Aku bukan pesimis, tak percaya ayat suci, Lang. Tapi aku sedar hakikat anak aku ni bukannya terkena buatan orang. Kalau ya, pasti ada tindak balas. Lagipun siapa nak berdengki dengan aku, Lang?”
“Itu ustaz, ini berubat kampung. Ada dukun yang hebat. Boleh sembuhkan anak kau itu. Iyalah, dengan izin Allah juga.”
“Entalah, Lang. Kasihan budak tu. Setahun berapa kali saja dapat pergi sekolah.”
“Tapi kadang-kadang aku rasa, sakit anak kau tu ada kaitan dengan saka belaan nenek moyang kita dulu-dulu. Kawan sepejabat aku ada anak macam kau. Sudah kronik sakitnya. Bila dia berubat kampung, rupa-rupanya ada 53 ekor jin saka di dalam tubuhnya. Mungkin sebab atuk nenek moyang budak tu dulu tak buang jin saka dari dalam badan sebelum meninggal. Jadi sakit itu menjadi-jadi bila jin-jin itu mengganggu metobalisme dan bahan kimia dalam tubuh badan budak tu. Aku bukan reka cerita, Ngah. Aku sendiri teman kawan aku bawa anaknya berubat.”
“Ha? Apa yang kau mengarut ni! Aku tahu Adib tu anak buah kesayangan kau. Tapi jangan sampai kau takutkan anak aku dengan cerita karut kau ni. Sejak bila pula nenek moyang kita bela saka? Ah, mengarut!”
“Itulah kau, Ngah. Dulu-dulu masa arwah Tok masih hidup kau jarang balik kampung. Dah berapa puluh doktor kau jumpa, semua kata anak kau sakit sebab genetik. Tapi keturunan kita ada ke yang gatal-gatal kulit macam dia?”
Adib bersandar ke tepi dinding memerhatikan pertelagahan ayah dan Mak Langnya sambil tangan kirinya tidak henti-henti menggaru pelipat tangan kanannya juga leher dan pipi serta kulit kepalanya yang berkerak.
“Betul ke kau nak jadi arkitek bila besar nanti?” Bahri berani menyoal setelah terlihat cita-cita yang ditulis Adib sewaktu disuruh oleh cikgu Solehah memandangkan dia duduk bersebelahan Adib dan tulisan ‘ARKITEK’ itu boleh tahan besar.
“Ya. Kenapa?” Adib mula melakar sesuatu pada buku lukisannya menggunakan pensel 2B.
“Boleh ke kau nak jadi arkitek?” Bahri meneleng kepalanya, cuba melihat apa yang sedang dilakar oleh Adib.
“Kenapa pula tak boleh?”
“Eh, kau tak tahu ke yang kita ni belajar aliran Sastera, bukan Sains. Kalau kau nak jadi arkitek, kau kena belajar apa yang budak kelas Sains sekarang tengah belajar. Fizik, Matematik Tambahan dan yang lain-lain tu.”
“Macam tu ke? Siapa yang bagi tahu kau? Aku tak tahu pun.”
“Kau memang tak tahu, Dib. Sekolah pun kau jarang datang. Sistem pendidikan kat Malaysia memang macamni dari dulu lagi.”
Adib masih tidak berhenti melakar sesuatu pada kertas lukisannya.
“Kelas Sains itu khas untuk budak-budak bijak pandai. Macam aku ni memang pemalas, diletak di kelas Sastera. Sama macam kau, Dib. Ponteng memanjang.”
Dalam tak sedar lakaran Adib yang selalunya kemas sempurna menjadi hodoh sekali. Hanya ada contengan-contengan yang tidak difahami sesiapa, kecuali dirinya yang tiba-tiba terasa kecewa dan tersangat nyeri hati.
“Kalau begitu, tak usahlah Cikgu Solehah menyuruh menulis cita-cita di atas kertas impian yang dimasukkan ke dalam balang kaca.” Adib berdesus sendiri.
Jika dibandingkan Mak Lang dengan adik-beradiknya, Mak Langnya lebih alturis. Adib terkenang sewaktu dia darjah tiga, Mak Lang berjaga sepanjang malam dengan tidak melepaskan sesisir sikat di tangan. Mak Lang memang biasa menemaninya tidur. Barangkali, menurutnya kerana ibu saudaranya masih belum mempunyai suami juga anak kecil seperti emaknya, jadi dia menumpang tidur di bilik Adib bagi menghilang bosan. Namun, di tangan Mak Langnya yang terdapat sesisir sikat itu, seolah-olah tidak mahu berhenti menggaru tubuhnya yang kegatalan dari malam ke pagi.
Tidak seperti adik-adik perempuannya. Jika demartisis atopik ganas menyerangnya, dia akan berubah menjadi seorang abang yang tidak diselesai. Adib tidak mampu melupakan saat dia sekeluarga pulang ke kampung untuk berhari raya, kulitnya terlalu gatal sehingga dia tidak mampu berhenti menggaru. Nanah mula keluar daripada permukaan kulit setelah trans epidermal water loss berlaku dan sarafnya mulai gatal tanpa mampu dikawal lagi. Waktu itu, saat seluruh ahli keluarga berkumpul di ruang tamu untuk bersalaman dan bermaaf-maafan, Adib mengunci diri di dalam bilik tidur agar bau nanah daripada tubuhnya tidak mencemari kemeriahan Aidilfitri seisi keluarga.
“Abang duduk jauh sikit, boleh?”
“Kenapa abang tidak mandi?”
“Kenapa rambut dan kening abang gugur?”
“Lantai rumah penuh dengan kulit kering abang yang terkupas. Lebih baik abang duduk di bilik saja.”
Adib memandang lagi hamparan peta di hadapannya. Peta itu tersangat luas meskipun saiznya lebih kecil daripada saiz dinding. Baru-baru ini dia banyak membaca tentang pembinaan-pembinaan agung di dunia, meski dia tahu disebabkan dia budak aliran Sastera, maka mustahil dia dapat melunasi cita-citanya dengan cara terindah. Setelah ditekuni sejarahan pembinaan dan peradaban, dia menemukan binaan yang lebih indah daripada Menara Eiffel yang selalu dipuja itu. Rupa-rupanya, Masjid Agung Djenne di kota kecil Mali, Afrika Barat lebih hebat daripada menara obelisk di Eropah.
Adib melakar dan terus melakar. Hasil tangannya selalu mendapat pujian Mak Lang kerana Mak Lang satu-satunya yang meraikan semangat juga cita-citanya. Pelbagai bentuk bangunan dilukis. Terkadang, dia melukis landskap. Tidakpun jika bosan, dia melukis alam nan terbentang luas. Melukis semula apa yang dilukis terlebih dahulu oleh Tuhan yang Maha Sempurna dalam mencipta.
Musim pandemik pula belum reda, tetapi adik-adiknya sudah mendapat seragam sekolah baharu. Dia bangga kerana orang tuanya tidak pernah sekalipun culas tentang pemakaian anak di sekolah. Adib tidak meminta seragam baharu. Seragam sekolahnya yang dahulu masih elok kerana jarang dipakai dan lebih kerap digantung pada penyangkut baju. Hasil rawatan di Klinik Khizan, kulitnya kelihatan bertambah sihat. Sambil merenung lembar kalendar yang dipenuhi kotak-kotak terkandung tarikh, dia menyoal dirinya.
“Akan bersekolahkah aku esok hari?” – Mingguan Malaysia