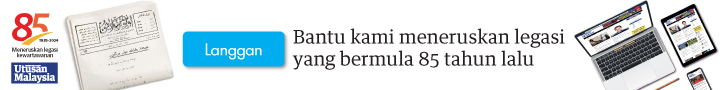JAKARTA: Sebuah rumah perlindungan yang dulunya dihuni oleh pelarian etnik Cina zaman peperangan dan pembunuhan secara beramai-ramai Suharto kini menjadi tempat tinggal kepada beberapa keluarga miskin.
Lapor South China Morning Post, Sutikno Djiyanto, warga Indonesia berketurunan Cina merupakan penjaga bagi rumah dua tingkat terbengkalai di Surabaya, Indonesia yang sebelum ini menjadi rumah tinggalan.
Bangunan berusia dua abad itu dikenali sebagai Gedung Setan kerana lokasinya sebelum ini dikelilingi tapak perkuburan, pernah menjadi rumah perlindungan kepada pelarian akibat kekejaman komunis pada 1948.
Mendiang ayah Sutikno `berlindung’ di bangunan berkenaan pada tahun yang sama malah Sutikno sendiri dilahirkan di sana pada 1957.
Kini, rumah itu menjadi tempat tinggal kira-kira 150 penduduk miskin daripada pelbagai latar belakang etnik dan agama.
Sutikno, 63, yang dikenali dengan nama panggilan Cina, Djie Djwan Tek menjaga komuniti yang tinggal di bangunan itu melalui pendekatan sosial.
Beliau hanya mengenakan bayaran bulanan kira-kira 15,000 rupiah (RM4.29) kepada setiap isi rumah bagi menampung kos penyelenggaraan, cukai hartanah dan pampasan faedah kematian.
Bayaran bulanan sebanyak 5,000 rupiah (RM1.42) pula dikenakan bagi setiap individu untuk penggunaan bilik mandi, sinki dan tandas.
Penduduk yang menetap di rumah tersebut tidak dikenakan sewa, sekali gus menjadikannya `perumahan yang amat murah.’
“Asalnya, orang-orang Cina yang menetap di bangunan ini tetapi kami kini hidup secara asimilasi sejak empat generasi lalu.
“Ada campuran orang Jawa, Sumatera, dari Kalimantan. Inilah Indonesia,” katanya.
Jelasnya, dia terpaksa memikul tanggungjawab besar untuk terus menjaga rumah dan penghuninya kerana diberi kepercayaan untuk melakukannya.
“Mereka seperti saudara saya di bawah satu bumbung, jadi saya harus melayan dengan baik sekali, saya tidak boleh melakukan apa sahaja sesuka hati,” ujarnya.
Dalam pada itu, seorang pensyarah arkitek di Petra Christian University di Surabaya, Handinoto mendakwa bangunan itu sebelum ini pernah menjadi milik kerajaan kolonial Belanda dan telah digunakan sebagai ibu pejabat pentadbiran di wilayah timur Jawa.
Katanya, selepas pemimpin politik, Herman Willem Daendels menjadi Gabenor Belanda pada awal abad ke-19, ibu pejabat itu dipindahkan ke lokasi lain dan bangunan itu terbengkalai.
Menurutnya, seorang doktor berketurunan Cina, Teng Sioe Hie kemudian membeli bangunan tersebut dan ketika konflik 1948, beliau membenarkan ratusan pelarian etnik Cina dari tengah dan timur Jawa untuk menetap di sana.
Jelas beliau, Sioe Hie telah meminta ayah Sutikno untuk menguruskan rumah tersebut selepas tahun 1948 dan kemudian meninggalkan tempat tersebut.
Tambah beliau, bangunan berusia 200 tahun disenaraikan oleh kerajaan Surabaya sebagai `cagar budaya’ atau bangunan warisan.
Sementara itu, seorang penduduk menetap di bangunan itu, Elly Kusuma, 43, berharap dapat berpindah ke tempat yang lebih selesa kerana dia tinggal di dalam sebuah bilik kecil bersama suami dan tiga anaknya.
“Saya sering melihat tikus, nyamuk dan lipas di rumah. Saya memang mahu keluar dari sini kerana anak-anak juga tidak berasa selesa,” katanya.
Jelas Elly, dia masih ingat, ketika kecil ibunya pernah menceritakan bagaimana bangunan tersebut memberi perlindungan kepada pelarian etnik Cina seperti dirinya.