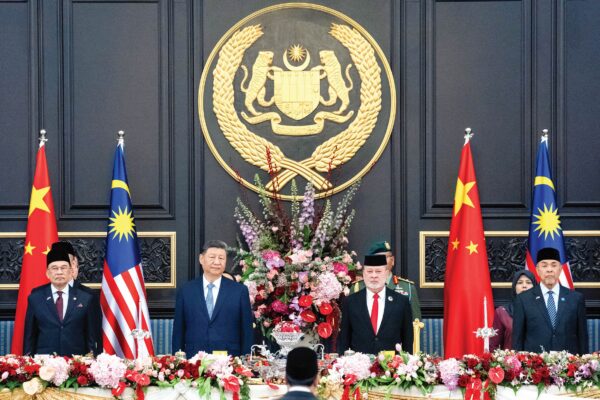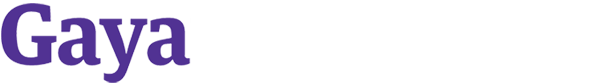MENJADI seorang marhaen di zaman sekarang adalah satu keistimewaan. Aku dapat merasakan segala kemajuan pada zaman ini. Jauh berbeza dari zaman orang tuaku. Walaupun tak kaya, aku masih mampu memiliki telefon pintar. Kalau dulu, aku hanya mampu memandang telefon Nokia yang menjadi kegilaan remaja.
Sekarang, aku boleh melayari Internet melalui telefon pintar tanpa perlu duduk di kafe siber dan baca berita terkini tanpa perlu beli surat khabar. Untuk membayar segala bil, semuanya di hujung jari. Membeli barang juga secara dalam talian. Dengan telefon pintar, semua kemudahan ada di dalamnya. Apa yang penting bil internet perlu dilunaskan setiap bulan.
Tapi aku pernah menyoal diriku sendiri. Apakah hidup di zaman ini betul-betul mudah? Apakah benar sekarang zaman boleh dapatkan apa saja tanpa batasan?
“Ah, susah betul sekarang nak beli rumah. Rumah mahal,” keluh rakan sekerjaku, Han. Aku yang masih duduk di rumah sewa mengakui kebenaran itu. Harga rumah meningkat seiring dengan peningkatan harga barangan dapur, saling berlumba sehingga aku tak tahu siapa pemenangnya. Yang pasti, aku kalah dalam perlumbaan kenaikan harga kerana awal-awal lagi penyata gajiku angkat bendera putih.
“Semua benda naik harga, Han. Bila harga minyak naik, harga barang pun naik, harga servis pun naik. Semuanya naik, yang turun cuma hujan.”
“Bagaimanalah generasi anak-anak kita nanti, Yuli. Kau sendiri harap menumpang di rumah sewa dan aku pula masih duduk di rumah mak ayah aku,” luah Han lagi kepadaku. Aku tersenyum pahit. Teringat kepada rumah yang tumbuh seperti cendawan, menunggu untuk dimiliki. Tapi hakikatnya hanya mampu memerhati. Dari mata, turun ke hati. Lama-lama, sakit hati.
Kata orang, zaman sekarang begitu mudah untuk menambah pendapatan sampingan. Boleh jual produk atau perkhidmatan dalam talian, boleh jadi ejen jualan atau buat pengiklanan perniagaan. Platform berbisnes secara maya begitu banyak. Cuma, kemudahan ini juga memudahkan penipuan. Di saat ramai peniaga lahir, penipu juga datang sebagai pakej terselindung. Belum lagi peniaga yang tersungkur akibat hutang bank tapi bisnes tak laku. Makin bertambah ruang, makin banyak juga risiko. Rasa curiga telah membataskan aku untuk mencuba. Rasa paranoid juga tumbuh seperti cendawan.
“Awak, kita belum beli barang anak. Anak nak sekolah.” Suatu malam, aku mengingatkan suamiku keperluan persekolahan anak sulung kami yang berada di Tahun 2. Kasut sukan belum diganti. Baju sekolah juga begitu cepat mengecil. Pensel juga selalu hilang entah ke mana, barangkali berjalan-jalan ke bekas pensel murid lain dan tak mahu pulang.
“Zaman kita sekolah dulu tak ada bantuan persekolahan macam sekarang. Ada banyak pilihan barang sekolah, ikut selera kita nak yang berjenama atau tidak,” ujar suamiku lagi. Aku tertawa.
“Bantuan sekolah tak ada, gaji tak besar, pilihan pun tak banyak. Yang bagusnya, nafsu belanja tak besar dan harga barang pun tak begitu mahal. Maka, keadaan masa lalu cukup sederhana.”
Suamiku memandangku dengan dahi berkerut, seolah-olah memikirkan sesuatu. Aku memilih untuk tidak bertanya, sebaliknya menunggu pertanyaan darinya sambil melipat pakaian berlonggok di dalam bakul. Sambil melihat aku melipat dan merapikan pakaian, akhirnya dia pun mengajukan soalan padaku dengan wajah ingin tahu.
“Apa pendapat Yul? Orang tua lebih beruntung dengan zamannya atau kita tak beruntung hidup di zaman ini?”
“Setiap zaman ada ketidakberuntungan. Mungkin, kita rasa lebih tertekan kerana zaman kita dipenuhi dengan tekanan. Semuanya mudah, termasuk mudah dapat tekanan.”
Tekanan. Aku menekan-nekan doh tepung yang kuuli untuk dijadikan kuih makan petang. Bukannya aku tak boleh beli kuih di gerai. Tapi aku cuba menjaga perbelanjaan. Kadang-kadang sedih juga tak dapat membantu peniaga, kewanganku terbatas. Aku tahu masalah peniaga yang tidak untung, sekadar dapat modal sahaja kerana harga barang naik. Apabila harga makanan dinaikkan, pelanggan juga takut untuk mendekati. Itulah dilema peniaga. Mereka sukar mendapatkan pelanggan, sementara pelanggan seperti aku terpaksa menahan diri dari keinginan kerana mengenangkan keperluan.
Bayangkan, gajiku bekerja sebagai kerani syarikat percetakan hanya bertahan seketika. Dari bank duitku datang, kepada bank juga duitku pulang. Begitulah, aku belajar membuat kuih dari Youtube yang diselangi iklan 5 ke 10 saat. Belum mampu aku melanggan Youtube premium hanya mahu mengelak iklan.
“Yul, buat apa tu?” Tiba-tiba jiran sebelahku menyapa, kebetulan lalu di tepi rumah sewaku sambil mengangkat baldi. Kulihat banyak kain jemuran di ampaian. Aku dengar dia mengambil upah cuci dan lipat pakaian di hujung minggu untuk tambah pendapatan. Kadang-kadang aku rasa, kerjaya zaman lalu berulang semula di zaman ini. Semuanya demi rezeki halal.
“Tengah buat kuih donat, kak. Untuk minum petang.”
“Pandai kau buat kuih. Sebelum ini kau buat kuih keria, sekarang kuih donat. Boleh buat bisnes, jual depan rumah,” cadang jiranku yang biasa dipanggil sebagai Kak Sal. Kak Sal otak bisnes, dia selalu mendorong aku untuk membuka gerai kuih untuk tambah pendapatan. Cuma, aku tahu harga barang tidak semudah membuat kuih.
“Tepung naik harga, kak. Itu baru buat kuih-kuih biasa. Belum lagi kos buat kek.”
“Alah, kau kurangkan bahan dalam adunan. Jadi kau taklah rugi sangat.” Aku yang pernah menjadi mangsa karipap berintikan angin dan pai ayam yang tak ada secebis daging ayam akhirnya hanya mampu tersenyum pahit. Ya, bisnes jual makanan paling cepat menjana keuntungan sebab manusia sentiasa makan. Cuma, hal yang bersifat nafsu ini tidak akan tahu makna setia. Kalau sudah bosan makan kuih donat, pelanggan akan cari kek keju. Belum lagi kira tahap kebersihan peniaga. Maka aku puji peniaga yang gigih dan jujur, sedangkan aku tidak dicipta untuk berani menipu dan tahan maki.
Bila bercakap tentang makanan dan betapa manusia sangat perlukan makanan untuk terus hidup, aku selalu merenung troli pasar raya dan meneka-neka berapa agaknya duit yang harus kubelanjakan untuk melihat troli itu sarat dengan barang-barang?
“RM50 tak rasa langsung bila dah hulur beli barang. Dapat baki seringgit dua ringgit, padahal beli dua barang je. Kadang-kadang dapat baki sen, barangnya cuma satu.” Begitulah ayat yang biasa kudengar pada zaman sekarang. Sedangkan dulu, 10 sen dapat beli minyak tanah beli gula-gula beli keropok. Hanya 10 sen, kata ibuku. Kalau 10 sen era 60-an itu dibawa ke zaman sekarang, entah berapa nilainya.
Kemudian, aku terdengar keluhan anakku setelah pulang dari sekolah. Dia mengadu bekal makanannya tak seenak bekal makanan kawannya. Terus aku bertanya apa yang dibawa kawan anakku ke sekolah sehingga timbul rasa cemburunya?
“Kawan kita bekal burger, spageti, sosej, kentang goreng. Kita cuma bekal sandwich je.”
“Tak apalah. Yang penting kenyang.”
“Kita ni miskin ke, ibu?” soal anakku, polos. Tapi pertanyaannya menyambar cuping telingaku seperti kejutan elektrik.
“Kenapa cakap macam tu?” Balasku semula, cuba menenangkan diri sendiri.
“Tak, adik cuma nak tahu. Kalau kita tak kaya, adik kena lebih rajin belajar supaya nanti adik dapat bantu keluarga jadi kaya,” kata anakku lagi.
Pada saat itu aku sedar anakku tidak berniat mahu menyinggung perasaanku tapi pertanyaannya tadi adalah rasa ingin tahu. Apakah hidupnya miskin? Apakah kami miskin? Adakah menjadi miskin itu hal memalukan? Adakah miskin itu label yang mudah diterima di zaman semuanya dikatakan mudah? Apakah pemilihan makanan menjadi satu-satunya penanda aras kemampuan sesebuah keluarga? Kemudian, timbul satu akal untuk aku menerangkan bahawa orang zaman sekarang sebenarnya tidak miskin.
“Esok ikut ibu pergi beli barang dapur. Ibu teringin nak makan sandwich tuna.”
Anakku mengangguk, membayangkan rasa seronok menyorong troli esok hari. Aku tahu troli itu takkan dipenuhi barang-barang. Troli itu menjadi kenderaan untuk anakku menjelajahi pasar raya, menjelajahi makna harga barang yang sukar diramal seperti ramalan cuaca. Malah, roda troli yang sering terhoyong-hayang itu sendiri seperti keadaan hidup manusia di zaman ini. Disorong ke kiri, membelok ke kanan. Disorong ke kanan, membelok ke kiri.
Keesokan harinya, setelah mengambil anak di sekolah, aku membawanya ke pasar raya seperti dijanjikan. Seperti biasa, anakku menceritakan bekal makanan kawannya yang enak. Aku mengangguk-angguk mendengar ceritanya. Setelah kaki melangkah masuk ke ruang pasar raya, kami berdua menjelajah pasar raya dari lorong ke lorong. Aku memberitahu, seikat sayur berapa harganya, sekampit beras 10kg berapa banyak kenaikan harganya, sebungkus roti pula berapa harga terkini. Harga makanan tak pernah setia. Selalu berubah. Sampailah ke bahagian makanan dalam tin, anakku melopong.
“Mak, setin tuna ini lebih kurang sama harga macam nasi ayam sepinggan.”
“Haa, abang nampak tak? Sandwich tuna adik tu mahal. Abang bukan orang miskin.”
Kemudian, kami berjalan ke bahagian telur ayam. Ada pelbagai jenis telur ayam. Telur kuning biasa, telur ayam kampung, telur omega, telur ayam organik dan entah apa lagi namanya. Menyebut gred telur saja anakku sudah dapat belajar abjad A sampai E. Apabila melihat harga telur yang selalu dijadikan bahan utama sandwich yang dibawanya sebagai bekal ke sekolah, matanya terbeliak.
“Wah, mahal juga telur ayam rupanya!”
“Nampak tak? Bekal adik ke sekolah tu tak semurah yang adik fikir.”
“Kenapa telur mahal? Ayam tak bertelur banyak ke?”
Aku tertawa. Aku tak tahu bagaimana untuk menjawab soalan itu. Anakku terlalu muda untuk memahami permainan permintaan dan penawaran. Malah orang dewasa juga kadang-kala lupa betapa terbatasnya kemampuan untuk memiliki banyak benda.
Usai membeli roti, telur dan setin tuna yang mahal tak setimpal dengan saiz, aku kembali ke bahagian makanan dalam tin. Aku terfikir mahu buat karipap inti sardin, entah kenapa tiba-tiba mengidam. Aku berdiri di depan rak makanan dalam tin dan melihat tin-tin sardin disusun kemas. Kelihatan begitu istimewa dan bertambah tinggi darjatnya. Pada saat itu juga aku tersenyum pada tanda harga setin sardin yang dulunya makanan marhaen tapi kini menjadi makanan mewah. Perlahan, anakku merangkul tanganku dan berkata dengan wajah terharu.
“Ibu, rupa-rupanya semua bekal sekolah adik tak murah. Kita bukan orang miskin. Selepas ini adik takkan cemburu lagi dengan bekal makanan kawan-kawan adik.”
Kami berdua akhirnya melangkah keluar dari dunia harga bersama pemikiran berbeza. Anakku percaya dia tidak miskin, sedangkan aku sedar aku tidak kaya. Pada saat itu aku berfikir. Harga sardin juga tidak serahmah dulu. Zaman sekarang, selain dunia di hujung jari, dunia juga ada banyak kemahuan. Hakikatnya, segala kemahuan ini aku merasai lebih banyak keterbatasan. Aku seperti sardin, hidup dalam sempit tin. – Mingguan Malaysia