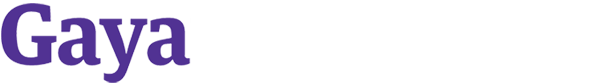“Selamat Hari Raya ayah, mak. Maaf zahir batin?” ayat lazim ketika aku salami mereka. Inilah rutin saban Syawal kami pascaperkahwinan. Pernah sekali sahaja kami beraya di rumah sendiri ketika isteri berpantang.
Kami berehat di anjung sambil berbual kosong menantikan waktu iftar akhir. Rasa letih memandu membuatkan mataku agak mengantuk. Semilir senja yang nyaman tambah meningkatkan lagi rasa ingin lena. Namun suasana menjelang Maghrib yang lama tidak kurasakan membuatkan aku berjaya menewaskan rasa kantuk itu.
“Assalamualaikum, mak hajah!” Sebentar, kedengaran salam diutus. Jiran-jiran mula menyerang. Tak sempat nak salin bekas, datang lagi seorang dua tetamu. Aku dan isteriku cuma jadi tukang sambut, sementara emak dan adikku salin lauk dan isi dengan lauk kami pula.
Cerah mataku apabila melihat aneka lauk dilambakkan di atas meja. Sehari sebelum lebaran, jiran tetangga sudah mula menghantar juadah. Adat ‘munjung’ yang telah sekian lama diamalkan tetap menjadi salah satu etos Hari Raya di perkampungan ini.
Variasi juadah dari yang berat seperti ketupat, lemang, nasi impit, dan nasi beriani kepada aneka lauk dan kuih-muih. Mendahului senarai sudah pasti masak lodeh, rendang, sambal goreng, serunding dan macam-macam lagi. Kuih tradisi pula seperti dodol, wajik, bahulu, tumpi serta kuih bangkit turut dalam senarai.
“Wah, banyak benar hidangan buka puasa kali ini, mak!” Aku teruja. Suasana ini memang kami nanti-nantikan, biasa berbuka ala kadar saja. Iyalah juadah beli, banyak mana sangat. Cuma masalahnya, nak sental di mana? Perutku kecil.
Selepas memimpin bacaan doa, aku jadi serba-salah nak mula dengan apa. Isteriku juga kelihatan rambang mata.
“Sokmom, cuba rasa rendang ni, Kak Yamah yang buat,” ujar bapa. Tersentak aku dengar nama itu. Siapa tak tahu kalau dia yang buat rendang, memang ummp! Segera pula aku capai bekas rendang dan adukan dengan ketupat.
“Hmm, memang kelaslah rendang Kak Yamah!” Komenku. Bapa tunjuk pula nasi impit dan kuah kacang. ‘Wah, tak boleh tahan ni!’ hatiku menggerutu. Perutku mulai padat, hidangan masih banyak yang belum aku jamah. Sudah beberapa kali aku sendawa.
Isteriku juga tak kalah hebatnya. Bukan sahaja makanan berat, malah kerepek, wajik dan dahlia sempat dicapainya. Dalam susas-susah menjaga kandungannya dan Faris, anak sulungku, masih sempat juga semuanya masuk ke tembolok. Hampir setengah jam juga kami di meja makan. Aku hirup pula air katira sebagai penutup. Kemudian kami mula merangkak untuk menunaikan solat Maghrib dengan susah-payahnya.
Ini belum Hari Raya lagi. Biasanya pagi esok lagi meriah acara ‘munjung’ masyarakat Jawa ini. Satu adat yang masih kuat dipertahankan oleh koloni etnik asal di Johor ini. Sikap saling membantu dan berbudi bahasa juga masih kukuh. Orang memberi, kita merasa.
Benar tebakanku. Seusai waktu subuh lagi jiran-jiran bertali-arus menghantar juadah serancak gema takbir yang bergaung di corong-corong radio. Kali ini daripada mereka yang agak jauh. Emak dan isteriku tak menang tangan meladeninya. Kami yang lelaki sibuk bersiap untuk ke masjid.
Aku dan Faris lengkap berbaju Melayu bersampin sedondon. Emak ajak kami menjamah sarapan dahulu sedikit. Memang itu antara perkara sunat sebelum solat Hari Raya. Aku meraba perut. Kenyang semalam masih terasa lagi. Tapi terliur juga tenguk hidangan yang baharu sampai.
Pandanganku tertumpu kepada menu yang baharu, burasak. Wah, semalam tak ada! Burasak ini jarang kujumpa. Orang Bugis sahaja yang mahir. Ini mesti dari Bachok, sebab dia sahaja satu-satunya keluarga Bugis di kampung kami. Lantas kuramahi juadah itu.
Apa lagi apabila digandingkan dengan rendang ayam dan kuah kacang, memang mengancam. Penuh semula perutku. Niat untuk berlama-lama di meja makan terbantut apabila isteriku mengingatkan waktu solat hari raya pukul 8.30 pagi. Ayah telah menanti di anjung.
Siap solat, aku balik terus ke rumah. Aku tidak turut serta ‘barakan’ orang kampung, iaitu kumpulan marhaban dari rumah ke rumah. Dulu, masa zaman sekolah, aku suka juga ikut kerana dapat duit raya yang agak lumayan.
Kemudian kami mula bermaaf-maafan. Adat orang Jawa sangat unik. Kami akan duduk bersimpuh, salam dan luahkan ‘kesalahan’ satu persatu. Ketika inilah jika ada kesilapan peribadi akan dilafazkan dengan ikhlas. Mohon halalkan makan minum dan luputkan segala dosa. Ada ketikanya hampir 10 minit adegan itu berlaku.
Air mata akan mengalir spontan dan suasana hening seketika. Isteriku walaupun orang Utara, akhirnya akur juga dengan cara kami. Malah dialah lebih menangis daripada kami pula. Entah-entah banyak dosanya kepadaku, hati nakalku mengusik.
ii
Sempurna ‘slot’ bermaaf-maafan, ayah ajak aku jenguk-jenguk dapur lagi, ‘mentong’ katanya. Tadi aku dan Faris dah makan sebelum ke masjid, bila kali kedua ini disebut ‘mentong’. Aku pandang isteriku. Dia mengisyaratkan dengan gerakan kepala kerana dia memang belum makan lagi.
Aku nampak satu lagi makanan tradisi yang digantung selari dengan ketupat. Biasanya orang kampung akan gantung ketupat yang telah masak pada sebatang kayu. Berselang dengan ketupat itulah kulihat beberapa batang lepat berjuntai. Ya, lepat!
“Ha, yang ini memang istimewa!” Jeritku sambil mencapai dua batang lepat dan kuletakkan di atas meja. Isteriku kaget kerana sebelum ke masjid tadi aku sudah makan banyak,
“Abang biar betul. Kata nak diet,” tegur isteriku seakan menyindir. Yalah, sepanjang bulan puasa berat badanku susut dari 82 kg ke 76 kg. Aku hanya hantar sengih sahaja sebagai proksi jawapan.
“Raya kan, jarang jumpa ni.” Aku sengaja cipta alasan. Tapi memang betul pun, bukan senang nak dapat menu langka begini. Pada hari-hari biasa tidak dibuat dan dijual orang, kecuali sesekali di pasar minggu, itupun jauh di pekan.
Aku buka balutan lepat yang panjangnya kira-kira 5 inci itu. Lepat ini dibalut dengan daun nyiur muda atau ‘janur’ macam ketupat juga. Bezanya ketupat berisi beras dan ada bentuk seperti ketupat bawang dan ketupat jantung. Tapi lepat ini berisi pulut dan sejak dahulu inilah bentuknya, memanjang.
“Wah, lepat kacang!” laungku. Mengejutkan isteriku yang baharu hendak menjamah ketupat daun palas pemberian jiran bercicahkan rendang.
“Ini memang special, cheq.” Aku sengaja menaikkan minatnya. Aku potong-potong lepat itu tiga keratan sebatang. Aku letakkan atas pinggan dan suakan kepada isteriku.
“Ha, dah dapat lepat kegemaran kau tu, Sokmom?” Entah dari mana tiba-tiba emak menegurku. Isteriku spontan memberi ruang dan menarik kerusi untuk mak mertuanya. Aku sengih melihat teguran emak itu. Dia tahu benar fiil aku jika bertemu dengan makanan kegemaranku itu.
“Marilah mak, makan sekali,” pelawaku berbasa-basi. Emak sudah lanjut usianya. Tetapi langkahnya masih laju. Dua tiga jenis lauk kalau sekali masak masih betah dia. Apatah lagi jika anak-anaknya balik menjelang Syawal ini, bersengkang mata sanggup lagi dia.
“Mak dah tak larat nak isi perut, Mom. Diana, dah rasa lepat Johor?” Emak melayan anak menantu kesayangannya yang sedang mengandungkan cucu keduanya itu.
“Yono yang hantar tadi. Katanya dia yang buat sendiri, mewarisi bakat bapanya.” Dam! Terhenti jemariku hendak menjamah lepat yang telah aku potong tadi. Jiwa tiba-tiba sentap. Seleraku lenyap.
Mengapalah emak sebut namanya ketika seleraku memuncak hendak menjamah lepat kacang ini. Kalau tahu dia yang buat, aku tak sentuh.
“Ya Allah, sedapnya!” Sekali lagi aku tersentak. Kali ini dengan jeritan isteriku tatkala masuk sahaja potongan lepat ke rongga mlutnya. Aku lihat dia ulang ambil keratan kedua dan ketiga menghabisi sebatang lepat yang aku hiris tadi.
“Tak pernah Diana jumpa sesedap ini,” omelnya lagi menambah rusuh di hatiku. Beberapa kali juga air liur bergeluk ke kerongkongku menahan rasa kempunan. Aku sengih-sengih juga mengiyakan kata-kata Diana. Emak pula tokok buka dan hiris lagi lepat menggantikan tugasku.
“Ha, Mom, kenapa tak makan? Tadi ghairah sangat,” emak buat aku sentap lagi. Aku jeling gelagat isteriku di sebelahnya yang semacam hendak habiskan semua lepat yang aku letak tadi.
“Ha ah, ya mak. Layan Diana dulu…” Aku buat helah bela diri. Dalam hati berperang sendiri. Rasa cemburu dengan selera dan aksi isteriku melantam lepat, berseteru dengan nama Yono yang emak sebutkan tadi.
Akhirnya aku hanya telan air liur melihat Diana melunasi kesemua lepat yang aku potong.
iii
Menghampiri tengah hari aku santai di ruang hadapan. Sesekali gerombolan kanak-kanak yang bertandang menyalami. Aku hulur sampul duit sekeping seorang. Memang telah aku niat infakkan sebahagian pendapatanku untuk anak-anak kampung pada setiap tahun. Aku tahu, itu antara keriangan mereka menyambut Hari Raya. Tiba-tiba datang sepasang tetamu dengan masing-masing mendukung anak kecil. Pakaian sedondong hijau lumut semuanya. Lelaki itu aku kenal persis. Berderau darahku menyirap ke kepala.
“Selamat hari raya Mom, bila sampai?” Mesra sahaja lelaki itu menyapaku. Lebih aku tergamam apabila dia menyalami dan mendakapku. Mentang-mentanglah penjarakan sosial sudah tidak terpakai, aku mendengus. Aku balas ucapannnya dan peluk juga tubuhnya yang lebih kekar.
“Ha, imam muda kita dah sampai, jemput naik!” Ayahku meluru menyambut ‘imam muda’ yang diungkapkannya. Aku gelintar semula kenangan lima, enam tahun lalu. Itulah antagonis yang menjadi dalang putusnya cintaku dengan Siti, gadis idamanku.
Aku raba pipi kananku. Masih terasa akan bengkak dan sakit kena tinjunya walaupun sudah sekian lama berlalu. Memang gaduh besar kami dahulu. Dan aku tahu Yono lebih gagah, lebih kuat. Aku tewas!
Tapi tidak mengapa bab itu. Kalahpun aku sempat lepaskan luku ke kepalanya. Yang lebih menyakitkan, aku juga tewas memenangi hati Siti! Tapi yang bersamanya ini bukan pula Siti. Aku buat analisis sendiri.
“Yono dah diangkat jadi imam muda masjid kita sekarang, Mom.” Ayah memberi jawapan tanpa aku cari. Aku paksa angguk melayan kata-katanya. Mataku menjeling wanita di sebelahnya. Betul, bukan Siti.
“Kenapa, Mom?” Rupanya Yono sedar aku sedang memerhati isterinya. Matanya buntang. Aku jadi kemalu-maluan, serba tak kena.
“Kita sama-sama tewas, Mom,” ujarnya semacam mengerti detik citra di hatiku. Dia sengih-sengih sembari mataku terkebil-kebil.
“Ini isteriku, Melati, bukan Siti. Lama kita tak ketemu, banyak benda dah terjadi.” Aku terdiam. Tak tahu nak sambut apa kata-katanya. Lewat enam tahun peristiwa itu berlaku, aku tidak mampu lupakan. Hinggalah aku meninggalkan kampung dan bina hidup sendiri.
“Nah, ini lepat kacang hari raya untukmu. Aku buat usaha kecil-kecilan mengekalkan makanan tradisi di samping membantu imam di masjid kita.” Aku nampak salju di wajahnya. Perlahan aku sambut seikat lepat yang masih hangat. Seleraku kembali memuncak.
“Terima kasih No, kita sahabat dunia akhirat. ” Aku genggam erat tangannya, memadamkan sekam yang tadinya berbara di dalam lepat pemberiannya. – Mingguan Malaysia