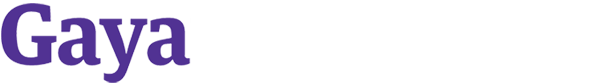Emak sungguh cantik. Apabila emak tersenyum, barisan gigi emak yang putih seakan memancarkan cahaya. Bulu kening emak hitam, elok terletak mengalisi matanya yang bersinar. Pipi emak dilatari lapisan putih yang mudah saja merona merah tatkala dijamah cahaya mentari.
Aku paling suka menatap wajah emak. Setiap kali terjaga dari tidur, tubuh langsing emaklah yang aku cari dulu. Emak akan memeluk, mencium pipi dan ubun-ubunku sambil mengingatkan aku melangitkan kesyukuran kepada Tuhan.
Ah, suara emak yang lembut dan lunak. Tubuhku menumbuh dan meninggi dengan air tangan emak yang enak. Di mataku, emak manusia paling sempurna. Bila besar nanti, aku mahu jadi seperti emak. Tenang, lembut dan penuh dengan kasih sayang.
Namun itu tahun-tahun ketika aku masih kecil dan mentah. Duniaku adalah dunia polos dan girang tanpa beban dan masalah. Ia rakaman musim yang kekal tersimpan di lipatan memori. Ayah dan emak yang saling mencintai, saling memberi hormat dan peduli hingga aku merasakan akulah insan paling bertuah memiliki keluarga sebahagia ini.
Entah bagaimana duniaku yang indah tiba-tiba dibadai awan hitam. Suatu hari, ketika aku terjaga di tengah malam yang pekat, aku ternampak emak memegang sekeping kertas. Bahu emak terhinggut-hinggut, makin lama goncangan tubuhnya semakin kuat namun aku tidak berani bangun mendekati emak yang tidak menyedari kehadiranku di sisi. Kertas putih sehelai itu dikeronyok emak, deru tangisnya melaju dan berlarutan sehingga aku bingung dan berkira-kira sendiri bilakah tangisan emak akan berhenti.
Mulutku berat untuk bertanya kepada emak, barangkali kerana aku tidak memahami apa yang terjadi lalu pantas sahaja peristiwa itu luput dari kotak ingatan.
Sepertinya sejak itulah tingkah laku emak berubah. Emak menjadi orang lain. Kerap termenung dan berdiam diri. Sorot mata emak jauh dan kosong. Wajah emak tidak berseri. Dan, kelibat ayah sudah semakin jarang kelihatan.
Ketika aku dan Nuha pulang dari sekolah pada suatu hari, langkahku mati ketika kakiku mencecah masuk ke dalam rumah. Sebaik pintu dibuka, aku nampak ayah tercegat tanpa suara. Ayah kemudiannya mengarahkan aku dan Nuha segera masuk, tiada pelukan dan kemesraan seperti yang selalu ayah lakukan saat ayah pulang dari berpergian. Riak wajah ayah amat sugul, angin seakan mati dan entah dari arah mana gegendangku menangkap bunyi esakan tenggelam timbul.
Ketika itulah aku terpandang emak di sudut rumah, dengan rambut kusut masai sedang tertunduk di atas kerusi rotan kegemaran ayah. Bahu emak sekejap-sekejap terhinggut namun tubuhnya longlai tidak bermaya. Entah kenapa aku seakan terpaku ke lantai. Nuha di sisi memelukku kebingungan. Pandangan kami tumpah ke wajah dan tubuh emak.
Emak mendongak, mendadak tangisannya pecah. Aku dapat melihat dengan jelas mata emak yang merah membengkak dan wajah emak yang sembab. Aku ingin berlari memeluk emak tetapi kakiku tidak bergerak walau seinci. Emak juga seperti ingin bangun memelukku sebelum aku menyedari tangan emak terikat ke belakang kerusi.
“Maaf Nurin, ayah terpaksa. Mulai hari ini, Nurin dan Nuha perlu memilih mahu mengikut ayah pindah ke tempat lain, atau mahu tinggal dengan emak.”
Petang itulah, gayung merah yang selalu emak gunakan menyirami tubuh kami, dan lantai bilik air tempat kami terlompat-lompat kesejukan ketika dimandikan emak selama ini, menjadi saksi isak tangis kami. Gayung itulah kami gunakan untuk mencurah air kuat-kuat ke lantai saat kami membawa diri ke bilik air, mengharap ayah dan emak tidak mendengar sedu sedan yang mendengungkan keliru dan bingung apabila disuruh memilih antara dua cinta yang besar dan agung.
Sekuat mana bahu kecil kami mampu menampung beban? Sedikit demi sedikit pohon kematangan menumbuh di laman nuraniku. Persoalan demi persoalan mengasak. Mengapa kelibat ayah sudah tidak kelihatan lagi dalam hidup kami? Apa yang terjadi sehingga ayah menggari emak di kerusi? Surat apakah yang memeras air mata emak dan menelan seri wajah emak yang menjadi kebahagiaanku selama ini? Adakah kami anak-anak yang terpaksa membuat pilihan yang sukar menjadi penyebab ayah sudah tidak kembali lagi?
Rakaman demi rakaman peristiwa kerap berulang-ulang di ruang mata namun semua pertanyaan hanya bergaung dan bergema di dalam dada, tidak mampu aku luahkan pada sesiapa. Aku menjadi pedagang diam, gemar menyembunyikan kata-kata dan teliti dalam menekuni hal-hal kecil yang melatari alam sekeliling. Daun-daun yang gugur, kicauan burung, deru angin dan cahaya matahari yang sering tidak dipeduli manusia menjadi alunan dan lukisan yang benar-benar aku nikmati. Aku cenderung memerhati dan meneliti riak wajah, bahasa tubuh dan tutur kata yang singgah di telinga.
Rupanya emak lebih cepat bangkit. Jiwa emak jauh lebih kuat dan harus aku banggakan melebihi kecantikan wajah emak. Kami memulakan hidup baru di kampung kelahiran emak, meninggalkan rumah sewa yang dihuni bersama segala kenangan masa lalu yang tidak mahu disesali. Sewaktu kami mengisi perut teksi dan tayarnya mula bergolek, aku melihat tidak setitis pun air mata emak tumpah. Emak langsung tidak menoleh kebelakang. Tidak ada tanda-tanda kesedihan di mata emak. Aku pantas menyedari emak bukan lagi emak yang dulu dipasung gundah dan kecewa. Wajah emak lebih tenang dan teduh, biasan jiwa emak yang kuat dan teguh.
Episod baru hidup kami bermula. Kehidupan kami sukar dan terasa janggal dengan ketiadaan sosok lelaki yang menjadi pelindung kami selama ini. Tiada lagi ayah yang selalu menghantar kami ke sekolah. Ketika bersedih, tiada lagi kata-kata ayah yang selalu menghiburkan. Ketika dirusuh kecewa, tiada lagi titipan kata-kata semangat dari ayah agar kami menjadi kuat. Kami merawat kesedihan, kesakitan dan kelelahan sendiri. Dunia aku dan Nuha hanyalah emak.
Di kampung, kami menumpang kasih uwan, mendiami rumah pusaka yang diteduhi rimbunan pokok durian, langsat, mencupu, pisang, manggis dan rambutan. Emak berdikit-dikit membina kembali kehidupan kami, berjualan kecil-kecilan di hadapan sekolahku dan Nuha. Gigih emak berjalan dari rumah uwan di hujung kampung, mendaki dan menuruni bukit, menyeberangi sungai sambil menjunjung dan menjinjit bakul jualan.
Ramai yang bersimpati dengan emak, namun aku melihat emak tidak pernah menunjukkan kesedihan malah emak sering saja menolak jika ada yang mahu menolong.
“Saya tidak mahu terhutang budi.” Begitulah selalunya emak mematikan asakan orang yang mahu menghulurkan bantuan.
Hari berganti hari. Jualan emak semakin laris. Gerai emak bukan sahaja dikerumuni pelajar-pelajar sekolah, emak sering mendapat tempahan dari guru-guru. Akhirnya, emak mampu menyewa rumah kedai Pak Berahim di tepi jalan besar.
Kedai emak meriah dilimpahi orang kampung. Emak menggaji pekerja untuk membantu. Aku dan Nuha turut menyingsing lengan apabila pulang dari sekolah. Sedari subuh, orang kampung yang pulang dari menoreh getah singgah membeli roti canai di kedai emak. Kedai emak menjadi tempat orang kampung bertemu, bertanya khabar dan bersembang.
Entah kenapa, aku mula berasa tidak sedap hati apabila terlihat lirik mata dan tutur kata beberapa pelanggan lelaki yang gemar bertandang ke kedai emak. Aku tahu hati budi emak. Emak amat menjaga diri, melayani pelanggan seikhlasnya, selayaknya sebagai seorang peniaga. Namun rambut yang sama hitam kadangkala tidak memiliki hati yang sama suci.
Aku baru tiba di rumah uwan ketika sayup-sayup suara herdikan di laman. Dari luar pagar aku melihat seorang wanita berdiri di hadapan rumah uwan, tangannya melibas ke kiri dan kanan sambil menjerit-jerit tanpa aku jelas butir bicaranya.
Tubuhku menggigil mendadak ketika deria keenamku terhidu amarah yang mengapung di udara. Langkahku menyumbing ke pintu dapur, menjauhi urusan orang dewasa. Bayangan lampau wajah ayah dan emak mengasak-asak, bersilih ganti dengan adegan yang terbentang di depan mata.
“Saya tidak pernah melayan melebihi yang sepatutnya kak. Saya berniaga, mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak. Saya masih waras kak. Saya masih isteri orang!”
Nada suara emak cukup kuat untuk aku dengari. Ternyata kerisauanku selama ini menjadi realiti.
“Oh, jadi selama ini engkau ini digantung tak bertali. Padanlah dengan muka. Ni, aku bagi amaran. Kalau aku dengar lagi orang kampung bercerita engkau menggoda suami aku, nahas!”
Kaki emak longlai, tidak mampu menampung tubuh lalu emak terduduk di tangga ketika satu tamparan tidak semena-mena mendarat di pipi mulus emak. Uwan menjerit, memeluk dan mempertahankan emak, berteriak menyuruh wanita itu pulang. Ah, aku sudah meningkat remaja, sudah mampu memahami duduk perkara. Sungguh hati aku tersayat melihat wajah emak, namun air mataku enggan keluar. Emak, begitu pekatkah awan hitam menyelubungi hidup kita?
“Dunia ini medan ujian. Kuatkanlah hati Nurin. Tingkatkan doa dan penggantungan kepada Allah.”
Tidaklah kami memulakan hari-hari yang baru melainkan aku menyaksikan emak bersujud dan berdoa pada kedinginan malam ketika fajar masih memencilkan diri. Aku dan Nuha semakin tegar menyendiri. Aku tidak mahu dianggap beban yang memberatkan orang lain.
“Jaga maruah dan harga diri.” Itulah pesanan emak dan uwan yang kerap diulang-ulang.
Sebesar mana keinginan kami mencorak kehidupan dan kebahagiaan, kami tidak akan pernah mampu mengatasi aturan Tuhan. Kehidupan ibarat pelayaran di laut lepas. Gelombang tetap datang. Ombak tetap membadai. Begitupun, waktu tenang tetap ada.
Ketika umurku mencecah satu setengah dekad, ketika itulah kami menerima berita. Ayah terlantar di hospital, tidak mampu bergerak kerana lumpuh separuh badan. Jiwa aku terasa kosong saat emak menyampaikan khabar. Aku menolak apabila disuruh emak menziarahi ayah.
“Nurin, walau bagaimanapun perit takdir yang kita lalui, ayah tetaplah ayah Nurin. Tiada apapun yang boleh memadamkan hakikat tersebut.” Aku tertunduk.
“Dalam hidup ini, kadangkala ada perkara yang tidak perlu kita tahu, malah lebih baik jika kita tidak mengetahuinya kerana ada banyak perkara yang berlaku di luar kawalan kita.”
“Emak tidak pernah mendidik anak-anak membenci ayah. Malah Nurin perlu berterima kasih kepada ayah kerana kalaulah bukan kerana ayah, emak sudah mengambil tindakan bodoh dan Nurin mungkin hanya dapat menatap jenazah emak sahaja pada hari terakhir kita bertemu ayah tempoh hari.”
Mata emak berkaca. Hati aku pecah, dan itulah harinya air mata aku mencurah-curah setelah sekian lama.
Ah, ayah. Sebenarnya aku rindukan ayah. Benar-benar rindu! Aku mengharapkan waktu dapat diputar kembali dan ayah masih tetap bersama kami melayari kehidupan sama seperti dahulu. Betapa bahagianya jika segala derita yang kami lalui hanyalah mimpi yang akan lenyap saat kami membuka mata.
Lalu, cinta emaklah yang membawa aku ke sini. Cinta ayahlah yang mengheret kakiku ke lantai hospital yang dipenuhi gelut resah dan kisah derita manusia. Langkahku mencari katil ayah terasa maha berat dan sukar, namun aku sudah berjanji dengan emak dan diriku sendiri untuk berani berhadapan dengan takdir.
“Nurin… Ayah minta maaf.” Bicara ayah tersekat-sekat, suaranya dalam dan aku menangkap getar di hujungnya.
“ Ayah banyak bersalah pada Nurin, Nuha dan emak. Ayah tersilap dalam membuat perhitungan dan pertimbangan. Hati ayah telah dibutakan oleh nafsu dan keegoan sendiri.”
Air mata ayah bercucuran, meluncur menyirami jiwaku yang dahagakan kasih sayang ayah. Aku tidak mampu berbicara dan tidak mahu berbicara. Biarlah ayah melepaskan apa yang terbuku di hatinya. Aku hanya mahu menjadi pendengar. Aku cuma mahu mendengar suara ayah.
Antara dua cinta, aku mahu mendakap kedua-duanya. – Mingguan Malaysia