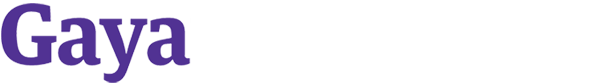DEMIKIANLAH aku membayangkan kemeriahan acara Festival Lagu dan Puisi itu yang julung-julung kalinya aku sertai. Ralit aku memerhatikan para peserta yang naik ke pentas membaca puisi masing-masing. Aku membatukan diri membiarkan fikiranku mengerewang ke pelosok pentas itu. Bagai terlihat-lihat seorang wanita lurus berkaca mata berdiri sambil memegang sehelai kertas dengan suaranya yang agak gementar. Sambil tangannya membetul-betulkan kaca matanya.
“Hmm… sudah baca sajaknya?” Aku berpaling. Wanita yang kelihatan anggun itu tersenyum menampakkan giginya berlapis. Puisi yang baru sahaja disampaikannya begitu memukau. Maknanya tersirat membuatkan aku merasa betapa kerdilnya diri.
“Belum!” jawabku polos sambil meraba isi beg mencari sekeping kertas yang telah kutulis puisinya.
Dua tiga baris puisi di kertas itu aku baca. Rasa macam semuanya tidak kena.
“Kalau nak baca jumpa urusetia,” bisiknya ke telingaku.
Aku menyeringai dan rasa hendak pitam membayangkan diriku yang tidak pernah naik mana-mana pentas tiba-tiba mahu melontarkan suara. Depan orang-orang hebat.
‘Jangan bodohkan diri sendiri Mai,’ aku bermonolog.
“Habis itu tak nak baca!” desak wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Dania itu. Aku masih terpegun melihat pemuisi dari negara luar.
Mereka sungguh berani melontarkan suara. Peserta dari Indonesia sedang memulakan bacaan sajaknya. Tegas dan lantang, sesekali nada suaranya mendayu dan merintih. Suaranya seperti berlari-lari ke telingaku.
Puisinya menjalar ke hatiku dan bermukim menjadi terumbu indah untuk aku semadikan di dasaran jiwaku. Di akhir bacaannya dia tunduk memberi hormat. Mahu sahaja aku berdiri dan memberi tepukan gemuruh.
Begitu juga dengan penyair dari Timur Tengah penyampaian puisi mereka yang bersahaja dalam bahasa ibundanya sedikit pun tidak memalingkan perhatianku untuk mengikuti bait-baitnya.
Malah aku kagum dengan keberanian mereka semua.
Kemeriahan kemuncak acara sedang bermula sebaik ketibaan Menteri Besar kemudian disusuli Sultan yang berkenan mencemar duli hadir memeriahkan majlis malam kemuncak.
Pelbagai persembahan dari Perak dihidangkan kepada penonton. Peserta luar bersilih ganti membaca puisi masing-masing dalam bahasa mereka. Memang meriah. Hatiku terbuai-buai.
Aku terpinga menyaksikan julung-julung kalinya persembahan yang begitu unik. Sungguh aku tidak berani menyaksikannya hingga selesai.
Dania yang dari tadi asyik bersembang dengan penulis di sebelahnya seperti hilang dari duniaku. Aku berada di dalam tarian itu. Memancak melompat bersama memegang patung kayu yang tiada berwajah itu.
Patung yang tidak berupa itu sedang dijulang dan diayak ke keliling pentas.
Badannya yang hanya separas pinggang tiba-tiba berisi dan berat. Aku panik dan berpeluh. Masakan patung kayu yang cuma sekeping papan itu tiba-tiba memberat dan sebaik aku mendongak mataku terbeliak melihat matanya bersinar memandangku seraya giginya menyeringai. Terasa duniaku mahu kiamat. Bahuku disentuh seseorang. Aku menekup muka. Nasib baik aku tidak menjerit.
“Mai! Awak ok ke?” Dania seperti mengejutkan aku dari mimpi panjang. Aku angguk terasa debaran singgah di dadaku.
“Dari tadi saya tengok awak tidak berkelip tengok tarian ‘Ghu! Ghu!’ tu,” ujarnya. “Jangan ngigau sudahlah” Akhirnya wanita itu tergelak di sisiku mungkin sedang membayangkan aksi aku ketika mengigau.
Tarian yang berhantu itu akhirnya ditamatkan dengan ‘ritual’ mengasapkan patung wanita yang sudah penat dilonjak dan dijulang. Terbayang bagaimana seronoknya patung itu tergelak. Alamak! Belum tidur aku sudah pun mengigau!
Wanita yang berbaju pink berbadan gempal itu melepaskan satu senyuman untuk aku.
“Akak, malam ni hanya yang terpilih sahaja yang membaca puisi. Akak boleh baca esok saja di dewan makan,” Kata-kata itu seperti satu jentikan kecewa ke jiwaku.
Nasib baik wanita bernama Suzi itu comel dan suaranya juga manja. Hmm… setidak-tidaknya membuatkan aku tenang.
Kertas yang bertulis puisi itu aku letakkan ke dalam beg tanganku semula. Aku duduk semula di sebelah Dania.
“Tak dapat baca. Esok?” soalnya seperti mahu terjongol biji matanya yang sepet itu. Gelihati bila mengenangkan riak wajahnya yang ‘comel’ itu.
“Hanya yang terpilih,” bisikku ke telinganya. Dia terdiam dan mencebik.
“Saya Dania,” wanita di depanku memperkenalkan diri sambil menghulur tangannya Suasana di dewan makan itu agak santai. Hanya bunyi sudu dan pinggan berlaga. Masing-masing sedang menikmati sarapan pagi dengan penuh harmonis. Itulah kenanganku pertama kali bertemu dengan Dania.
“Saya Mai, Maizurah!” sambutku sambil tersenyum.
“Penulis ke?” soalnya sambil menyudukan nasi lemak ke mulutnya yang comel.
“Adalah sikit-sikit,” balasku sambil memberitahu tajuk cerpen dan sajakku yang pernah tersiar.
“Tak sampai sepuluh,” akhirnya aku menamatkannya.
Tiba-tiba dia mengeluarkan beberapa buku dari begnya. Buku itu diletakkan di depanku.
“Wah! Inikah dia Dania Samsuri yang selalu saya dengar namanya,” Dia mengangguk teruja.
Aku teringat tentang sebuah buku di rumahku dan penulisnya kini berada di depanku sekarang.
Tanpa sedar aku sambar sebuah dari buku tersebut dan membayar harganya. Kenangan itu cukup indah kurasa dan beberapa keping gambar kuambil bersamanya untuk kenangan.
Buku yang siap bertanda tangan itu kupeluk dan dia cuma tersenyum memerhatikan gelagatku.
Beberapa tip penulisan diturunkan kepadaku. Wow! Beruntungnya aku. Aku berjanji akan memperaktikkannya sebaik pulang dari festival ini. Kami sempat bertukar-tukar cerita. Wanita kelahiran Johor itu begitu peramah. Memandangkan aku tinggal seorang di bilik dia menawarkan diri untuk menjadi rakan sebilikku.
“Mai! Jom balik, acara dah habis.” Dania sudah pun berdiri. Aku tersengeh melihat Dania. Wanita hebat yang telah menjadi ‘moderator’ siang tadi.
Sungguh! Dia wanita yang berkebolehan. Pantun yang diselangselikan dengan ucapan selambanya cukup membuatkan aku kagum. Orangnya tenang.
Aku masih dihantui pementasan tadi persembahan patung wanita, penari-penari yang mencucuk tangan sendiri dengan besi tajam. Pesilat-pesilat yang mempersembahkan aksi lincahnya.
Paling menarik melihat lelaki China yang berbaju seperti maharaja silam bermain-main dalam mindaku. Gerak tarinya ala-ala taici amat menghiburkan sekali.
Sambil bersilat lembut berus dicelup dalam dakwat dan sepintas lalu menconteng kain putih yang dipegang oleh beberapa pembantu.
Semua itu sangat mengagumkan aku. Lengan bajunya yang lebar terbuai-buai mengikut gerak badannya. Itu yang paling aku suka.
Tidurku seperti terganggu. Rakan sebilikku berdengkur kecil mungkin penat menghadam persembahan tadi. Tiba-tiba aku teringat kisah Hur Jun drama TV Jepun yang pernah aku tonton. Kisahnya sungguh menyayat hati. Banyak pengajaran yang aku dapat.
Pemuda yang mendalami ilmu perubatan. Namun banyak sungguh halangannya. Bahagian yang paling menyentuh hati apabila dia berhari-hari berjalan meredah beberapa perkampungan semata-mata mahu menduduki peperiksaan.
Konfliknya dia terperangkap antara keinginan dengan kewajiban. Sedih betul kerana dia tidak sempat sampai kerana terpaksa menolong sebuah kampung yang dilanda sejenis wabak. Dia telah menggunakan seluruh ilmu perubatannya. Namun sebenarnya itulah kejayaan kerana dapat membantu orang.
Pelbagai lagi konflik yang timbul. Ada lagi bahagian yang benar-benar buat aku menitiskan air mata. Dia terpaksa menurut wasiat tuan gurunya. Kerana taat dia menjalankan wasiat itu iaitu membedah mayat tuan gurunya sendiri untuk proses pembelajaran yang sebenarnya.
Memang aku ‘tabik spring’ dengan kisahnya. Tiba-tiba aku jatuh cinta dengan lelaki bernama Hur Jun itu. Orangnya tegas dan sangat berkarisma. Pandai betul orang Jepun buat cerita kalaulah diulang siarannya aku masih mahu menontonnya.
Aku cuba memujuk mata untuk lena. Adakah nasibku sama dengan Hur Jun datang sejauh ini hanya untuk gagal. Akhirnya aku terlena juga biarpun sesekali terkejut dan tersentak dengan igauan yang aku sendiri tidak pasti.
Sebaik terkejut dari lena Dania sudah bersiap-siap mengemaskan beg pakaiannya. Aku mencapai tuala bersiap-siap untuk mandi dan solat.
Ada program bacaan puisi di dewan makan. Kenapalah aku lambat tidur malam tadi. Semua ini gara-gara cerita Hur Jun. Aku memarahi diriku sendiri.
“Mai, aku terus ke jeti tau. Lagipun aku tak ambik bahagian dalam bacaan puisi. Kau pergi ya. Good luck!” Aku hanya memandang wanita yang kukenali selama empat hari itu berlalu pergi.
“Maaf! Maaf! Lupa nak salam,” Dania menyalami aku dan memeluk aku. Aku sudah seperti patung yang tidak bernyawa. Seramnya. Kenapalah aku asyik ingat adegan patung itu melonjak-lonjak.
Cepat kain baju kusumbat ke dalam beg. Beg yang agak berat itu aku seret hingga ke perkarangan dewan. Kulihat ramai yang sedang berebut menaiki teksi untuk pulang. Tanganku diseret seseorang.
“Jom balik! Kita naik teksi sama-sama,” Dania dan Hasnah berdiri di sisiku.
“Acara sudah tamat!” ujar Hasnah wanita kecil molek itu menamatkan angananku selama ini untuk mendebarkan diri berdiri di depan khalayak membaca puisi.
“Maisarah!” Aku berpaling mencari suara ala-ala lidah tersimpul.
Seorang lelaki merenungku legat. Bukuku berada di tangannya. Jari telunjuknya menunjuk ke kulit buku tersebut.
Wah! Hur Jun, bisikku. Aku berharap sangat lelaki China itu memakai baju tradisionalnya. Lelaki itu kelihatan segak dengan baju kemeja.
“Your mine?” soalnya. Aku angguk. Dia mengangkat tanda bagus. Aku tidak faham bagaimana buku keramat itu boleh berada dalam dakapannya.
“SEDETIK SENJA,” adalah buku kumpulan puisi sulungku.
“I like!” ujarnya.
“Thanks!” Malu pula aku. Hasnah dan Dania dari tadi terdiam di belakangku.
“Read for me, this one,” bersusah payah dia menyelak helaian buku tersebut.
Aku memegang buku tersebut. “Menanti Badai Membidas,” Aku membaca sebaris tajuk.
Aku pun membaca dari bait ke bait.
MENANTI BADAI MEMBIDAS
Tertulis periwayatan sebuah angkuh
dari pertapaan gunung bicara
mencarik kota hati
runtuh takhta peradaban
mempetirkan kilat lafaz memanah duga
berterbangan turun menyentuh
sayap seteru di gurun tandus.
Dengus sindiran memasung gentar
menabur debu sengketa
bermenterakan dendam irama
mencipta rentak cumbuan duka
terluka di gusi kata meninggalkan parut
sore yang terkunci pintu kebenaran
tersangkut di pelepah bibir
menanti badai membidas.
Dia kelihatan macam faham sahaja. Selesai puisi 20 baris itu kubaca dia memberi tepukan.
Baru aku perasan bukan dia sahaja yang memberi tepukan tetapi delegasi dari negara lain turut memberi tepukan siap mengangkat ibu jari. Aku tersipu. Hasnah mencuit aku dan membisikkan sesuatu.
“Aku dah rakam,” bisik Hasnah membuatkan keningku terangkat. “Terima kasih Maisarah” suara lelaki itu pelat.
“Puisi awak bagus, saya tersangat suka,” Tak sangka dia fasih berbahasa Melayu.
“Sama-sama Hur Jun.” Aku mengangguk. Dia juga mengangguk.
“Hur Jun?” soalnya sambil mengerutkan dahi. Aku cuma tersengeh.
Perlahan-lahan aku masuk ke dalam teksi melihat dewan yang penuh dengan peserta yang berebut-rebut menaiki teksi di pekarangan hotel. – Mingguan Malaysia