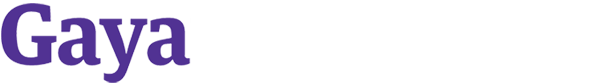RASA senak membuak-buak namun mana mungkin dapat ku rombak. Waktu bukan boleh diputar balik. Sungguhlah menyesal itu satu tanda ada sesuatu yang baik dalam diri tetapi bergunakah kesal saat itu? Belum duduk punggung sudah rasa melengas. Bagaimana hendak tinggal di tempat sebegini? Selama dua tahun pula.
Ah, gila! Baru kusedar idea itu idea untuk kerja gila. Berfikir untuk berpaling dan balik semula lagilah gila! Di mana hendak kuletak muka? Dalam akhbar tersiar, kawan-kawan satu Malaysia sudah tahu. Lantas aku bermanis wajah saat kupijak bumi Indo China, khususnya kampung Luas Halaman di pinggir Sungai Tonle Sap. Namanya kontras dengan rumah-rumah yang dibina rapat-rapat tanpa gang. Tidak usah sebut halaman, mimpilah itu. Teringat gambar fail di Arkib Negara sempena Pameran 100 Tahun Kuala Lumpur satu ketika dahulu. Terpapar gambar perumahan setinggan di Kampung Kerinchi dalam awal 70-an.
Sebaik turun dari pikap berinjin disel yang berbumbung separuh itu terus kusambar beg sandang dari lantainya yang berdebu. Karim Ma dan Fatimah Chu yang menjemput aku di stesen kereta api terakhir membawa aku ke rumah satu keluarga yang bakal menjadi keluarga angkatku sepanjang aku di situ. Sensitif deria bauku menangkap aroma lumpur dan hanyir kuala sungai yang selari dengan perkampungan nelayan. Air tengah surut, kuat bau selut, bolehkah aku bertahan?
Aku tiba ketika hari menjelang senja. Ada beberapa perempuan duduk di pelantar di hadapan rumah sambil bersembang dengan jiran atau memerhatikan anak-anak bermain di jalan sempit. Warga tua dan anak-anak lelaki satu demi satu meninggalkan rumah menuju masjid berdekatan untuk sembahyang Maghrib. Setiap warga desa yang berselisih dan ku tembung matanya begitu ceria lebih-lebih lagi bila sahabatku yang berdua itu memperkenalkan aku.
Bersalaman denganku sampai separuh bongkok! Ada juga yang mendakap seperti gelagat orang Arab. Begitu sekali penerimaan mereka. Aku pula yang tidak selesa dengan badanku yang pastinya bau mengalahkan haiwan zoo kerana belum mandi sejak kelmarin. Perjalanan jauh. Cahaya keikhlasan terpancar dari wajah mereka ketika menyambut salamku.
Ketika menyusuri gang setengah depa, langkah kakiku terpilih-pilih disumbangkan oleh taburan tahi ayam dan tahi kambing yang melata. Seperti penari zapin yang tidak reti, aku terjengket-jengket sambil tersenyum sendiri. Di hujung gang mati bertemu tangga sebuah rumah lama. Tiangnya tinggi, dari kayu jcengal yang ditarah dengan tangan. Bumbungnya genting lama sisik ikan seperti rumah agam di Terengganu, tetapi sudah banyak rongak disulam dengan plastik berwarna hitam. Dindingnya dari zink. Ketika itu aku terfikir, bagaimana panasnya rumah ini di watu siang. Tingkapnya kecil, hanya ada dua tiga. Inilah rumah yang aku bakal tinggal untuk dua tahun. Dua tahun kawan! Bukan dua hari atau dua bulan!
Aku anak metropolitan Kuala Lumpur. Dari keluarga kelas menengah. Aku besar di Taman Tun Dr. Ismail. Habis belajar di universiti aku terus dapat kerja. Letih dengan kerja rutin dan menyiksa. Jodoh yang kutunggu pun tidak sampai-sampai, asyik ada sahaja halangannya. Tiba-tiba mendapat cadangan dari seorang sahabat untuk pergi menjadi sukarelawan. Katanya, aku perlukan semangat baru. Aku perlu melihat hidup dari perspektif lain. Sambil itu aku dapat berbakti kepada umat Islam di negara mundur. Mudah benar aku terpancing. Terus mendaftar dengan Yayasan Salam untuk program Jambatan Kasih yang promonya tersiar di hampir semua stesen TV dan media sosial.
Sepasang warga tua menyambutku. Orang yang akan kupanggil ayah itu membahasakan dirinya sebagai datuk. Umurnya 65 tahun tetapi dia kata dia sudah bercucu yang umurnya sebaya denganku. Wajahnya legam dek dunia sungai dan laut. Kurus. Pipinya cengkung, kedutan penuh di dahi dan sekitar. Dia memakai kemeja biru lusuh dengan kain pelikat hijau berpetak dengan belang warna perang yang juga lusuh. Namun matanya memantulkan sinar keikhlasan dan kehangatan menyambut kedatanganku. Sebahagian rasa gusar membubar.
Isterinya bertubuh kecil, sedikit bongkok. Sebaik selesai kusalami tangannya, segera dia mengusap lengan dan kepalaku bagai aku ini budak kecil yang dikasihani. Runtuh tembok keterasingan yang terbina baru beberapa detik tadi. Disuruhnya aku segera mandi dan mengikut suaminya ke masjid kerana waktu Maghrib hampir tiba. Sejuk air telaga yang kutimba sendiri melempar pergi hamis bau badanku dan segala kerengsaan yang kutanggung sejak awal hari.
Masjid yang dibina dicelah-celah rumah itu adalah satu-satunya bangunan yang berbumbung tinggi di kawasan itu. Menghadap ke laut, di depannya tebing sungai dan jeti utama perkampungan. Dari jeti ke tangga masjid, dibina lorong pejalan kaki yang ditinggikan seperti jambatan kayu. Untuk mengelakkan becak waktu air pasang. Masjid itu kecil sahaja, lebih kurang saiz dua rumah bandung. Sungguh daif. Bumbungnya dari zink berkarat, tiada lelangit. Dindingnya sebahagian dari batu blok kasar yang tidak dikemaskan dengan plaster. Sebahagian lagi dinding papan pecahan kapal yang tidak dicat. Kolah tempat air sembahyang belum juga siap walaupun mula berkulat. Tikar mengkuang dan jerami menutupi lantai yang retak-retak. Di tepinya ada bangsal berdinding separuh, itulah sekolah dan madrasah tempat anak kampung ini belajar agama.
Memandang semua itu, kesedihan menurap seluruh ruang dadaku. Nyaris aku menangis kala senja yang langitnya merah jingga. Namun bila jemaah memenuhi ruang rasa bahagia turun bertandang. Seperti Hari Raya. Penuh masjid untuk hanya solat maghrib! Ah! Betapa berbezanya di sini. Tiba-tiba aku terlupa Kuala Lumpur. Aku ingin memberikan segalanya untuk tempat ini. Untuk saudara-saudaraku di sini. Yang tidak punya dana dari kerajaan. Segalanya adalah dari titk peluh mereka sendiri dan mereka adalah rata-rata nelayan ikan sangkar atau nelayan pesisir yang miskin. Pun kaya jiwanya. Rasa cinta tumbuh mendadak. Bermula hari itu, aku menjadi aku yang lain.
Kami bangunkan madrasah di sebelah masjid. Asalnya seperti kandang kambing. Bumbung atap nipah, dinding kayu-kayu dan lantainya tanah. Kami gunakan elaun bulanan kami bertiga untuk membeli zink, kayu, papan, kerikil, pasir dan simen. Tenaga kerja ialah penduduk dan anak-anak murid yang ada kelapangan di hari Jumaat dan Sabtu. Meja dan bangku pun kami tukangi sendiri. Enam bulan baru siap bangunan tiba Hari Raya Korban. Kawan-kawan dari KL datang. Dengan sumbangan mereka akhirnya siaplah madrasah yang ada enam kelas.
Hari-hariku penuh dengan kegiatan kerana murid-murid perlukan aktiviti lain seperti olahraga. Dapatlah kami tubuhkan pasukan bola sepak, badminton dan bola jaring. Mulanya ramai anak tidak ke sekolah kerana mengikuti ibu bapa mencari rezeki. Namun setelah melihat apa yang kami buat, ramai menghantar anak ke madrasah. Mengaji Quran dan asas-asas agama sekaligus dengan ilmu mutakhir. Yang tiada pelajaran sains komputer dan aplikasinya kerana tiada capaian Internet ketika itu.
Dua tahun rupa-rupanya masa yang singkat. Hari itu aku berangkat. Meninggalkan Kampung Luas Halaman dan kembali ke Kuala Lumpur. Tiba-tiba aku jadi begitu hiba. Keluarga angkat, anak-anak berkaki ayam dan berbau hamis, juga rakan-rakan sukarelawan sudah menjadi sekolah kehidupan. Dua tahun aku belajar erti kemandirian. Selama itu juga akal dan kudrat pecah sembilan memikir apa boleh dibuat untuk memandaikan umat. Aku guru Bahasa Inggeris, yang mengajar Matematik dan Geografi dunia. Mereka murid-murid yang mengajarku keperluan hidup, guna akal dan kemampuan untuk terus hidup.
Setua ini aku menangis saat mereka kusalami satu persatu. Berbaris sambil berselawat dari pintu masjid, ke jalan berturap tanah merah dan batu kerikil di mana pikup berbumbung separuh menunggu. Terasa amat kecil diraikan begitu. Sedangkan bukan banyak dapat kulakukan selama dua tahun. Aku kira aku yang lebih banyak belajar daripada mereka. Belajar menjala ikan, bertanam sayur di belakang dapur rumah keluarga angkat, belajar menukang dan membaiki masjid dan bangunan madrasah.
Setibanya di Kuala Lumpur, seakan aku kembali ke masa hadapan. Sehari dua berasa aku manusia yang sangat bertamadun. Berasa bangga bahawa tanah airku – bandar, pekan dan desanya cantik. Segalanya ada dan menjadi tumpuan rakyat asing mencari rezeki. Pun selepas sebulan dua kembali bekerja dalam pejabat nyaman berpendingin udara, aku merindukan Kampung Luas Halaman, di pinggir sungai berbau selut ketika air surut.
Selepas tiga bulan, biarpun gajiku besar. Hidup untuk wang dan survival diri. Berputar begitu sahaja setiap hari. Belum kira waktu habis di dalam kesesakan jalan raya atau beratur menunggu tren tiba. Benar, hidup dalam lingkungan keluarga, sahabat dan rakan sangat melegakan. Pun itukah kehidupan? Setiap hari berbuat untuk keuntungan syarikat gergasi demi mencari rezeki. Aku pun mulai mencari erti kehidupan, erti memberikan sumbangan, kebahagiaan hakiki. Lalu membanding akan rasa berguna, di sini atau di sana?
Emak dan Abah sering ingatkan tentang masa depan. Berjuang untuk orang itu baik namun perlu ingat juga untuk diri sendiri. Masa hadapan sendiri, keluarga, hari tua dan negara.
Aku berusaha bertahan hidup dalam kerangka masa hadapan. Mereka telah hidup lama dan pendapat mereka ada kebenarannya. Aku berusaha mencari pasangan, anak-anak saudaraku semakin ramai. Itu bermakna aku pun semakin tua. Lima tahun juga bertahan hidup di masa hadapan.
Akhirnya aku kembali ke Kampung Luas Halaman. Kembali hidup seperti kampung kita di masa silam.
Pun kali ini aku bawa perubahan – mengajar ICT kerana teknologi satelit dan tenaga solar sudah semakin mudah. Walau emak dan abah tidak berapa setuju aku teruskan. Kerana di sana pun aku membina masa hadapan. Kerana kita tidak pernah tahu banyak tentang masa hadapan. Aku kembali untuk masa hadapan. – Mingguan Malaysia