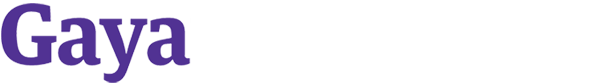“INI senarai nama penulis kayangan. Kamu tu termasuk dalam penulis kayangan ke?” tempelak Pak Somad. Matanya terbeliak memandang Rahmatan. Halkum Rahmatan turun naik.
“Penulis kayangan? Dalam sastera ini ada kelompok sastera juga ke, Pak Somad?” aju Rahmatan seperti kebingungan.
Pak Somad tidak menjawab. Dia memandang Rahmatan dengan renungan tajam. Rahmatan jadi serba salah.
“Biarpun aku dah lama menulis, nama aku ini tak pernah tersenarai dalam kelompok penulis kayangan,” Pak Somad bersuara dengan nada seperti merajuk.
Rahmatan tidak memahami maksud kata-kata Pak Somad. Usia Pak Somad sudah memasuki 70 tahun. Dia mengagumi Pak Somad kerana karya-karya Pak Somad yang hebat. Gaya bahasa cerpen Pak Somad cukup memukau pembaca. Malah sajak-sajak Pak Somad sungguh indah bait kata-katanya.
“Aku sedar diri aku ini siapa. Lulusan SPM sahaja. Itu pun lulus cukup-cukup makan. Para sarjana mana nak pandang aku penulis sekolah tak tinggi ini, Rahmatan!” suara Pak Somad perlahan sangat tetapi Rahmatan masih boleh mendengarnya.
“Apa maksud Pak Somad dengan penulis kayangan tu?” tanya Rahmatan yang masih kebingungan tidak faham. Tadi semasa dia sampai di rumah Pak Somad, dia terus menunjukkan sebuah majalah sastera yang khusus mengenai sastera. Terus air muka Pak Somad berubah.
“Aku ini tak sekolah tinggi. Jadilah aku ini penulis yang dipinggirkan. Para sarjana menilai sajak-sajak yang aku tulis itu bahasanya terus terang, tidak mendalam dan nipis pemikiran. Orang sastera kata aku ini tulis sajak prosaik,” Pak Somad meluahkan perasaan yang dipendamnya selama ini. Mulut Rahmatan melopong.
“Tapi saya tengok Pak Somad banyak juga terbitkan buku kumpulan cerpen dan kumpulan puisi. Saya sendiri sebagai peminat Pak Somad, buku-buku puisi Pak Somad saya dah khatam membacanya,” Rahmatan menyuarakan pandangannya.
Pak Somad mengangkat secawan kopi kemudian menghirup dengan bunyi di hujung bibir. Air kopi itu Pak Somad buat sendiri. Pak Somad tinggal berseorangan sejak isterinya meninggal dunia 10 tahun lalu.
“Takkan tengok saja air kopi yang aku buat itu. Tak sedap ke air kopi aku buat tu!” Pak Somad mempelawa sambil menyindir. Rahmatan tersengeh dan terus mencapai cawan berisi air kopi.
“Maknanya sepanjang penglibatan Pak Somad dalam penulisan, Pak Somad tidak pernah ditonjolkan sebagai penyair tanah air?” soalan yang tidak diduga itu terpacul daripada mulut Rahmatan.
“Kalau tak silap aku ada satu tulisan yang menceritakan penglibatan aku dalam penulisan. Itupun rencana sastera yang ditulis oleh wartawan akhbar. Aku dengar cerita wartawan tu sudah diberhentikan atas arahan orang politik,” jawab Pak Somad selamba.
“Pasal tulis cerita Pak Somad itu ke? aju Rahmatan spontan.
“Bukan sebab aku lah. Wartawan tu diberhentikan sebab tulis cerita pasal orang politik itu!” beritahu Pak Somad. Menganga mulut Rahmatan mendengarnya.
Entah kenapa hari ini Pak Somad banyak meluahkan perasaannya pada Rahmatan. Mungkin sudah lama Pak Somad memendamnya. Pada hal Pak Somad baharu sahaja mengenali Rahmatan. Jarak usia Pak Somad dengan Rahmatan terlalu jauh. Bagai usia datuk dengan cucu.
“Pak Somad ada dijemput ke majlis baca puisi?” Rahmatan bertanya lagi soalan yang ada kena mengena dengan dunia sastera. Menjadi kelaziman, penulis yang sudah menjadi terkenal dan digelar sebagai penyair, sering dijemput mendeklamasi puisi.
“Ada. Tapi aku ni bukan penyair kayangan. Jadi aku hanya dijemput baca puisi di kaki-kaki lima. Hingga ada yang menggelarkan aku penyair bawah tiang lampu,” ucap Pak Somad dengan suara perlahan.
“Maksudnya Pak Somad tak pernah dijemput baca sajak di majlis-majlis rasmi?” suara Rahmatan tinggi seperti terkejut.
Pak Somad menggeleng-gelengkan kepala. Dahinya nampak berkerut. Rahmatan berasa pelik dan tidak percaya. Masakan tidak pernah langsung. Sedangkan Pak Somad ramai peminatnya.
“Entahlah, Rahmatan! Aku sendiri pelik dengan dunia sastera kita ni. Seolah-olah ada kelompok dalam sastera. Penulis kayangan dengan penulis marhaen!” luah Pak Somad bernada kecewa.
“Tapi bukankah Pak Somad produktif menerbitkan buku puisi dan cerpen. Apakah mereka tidak menilai selama ini?” Rahmatan menerjah soalan sinis yang boleh membuatkan jantung Pak Somad seperti ditusuk anak panah.
“Aku terbit sendiri. Buku-buku aku bukan diterbitkan penerbit-penerbit berwibawa. Penerbit yang diiktiraf oleh MAPIM. Jadi ada kemungkinan buku-buku aku ditolak pencalonannya,” jelas Pak Somad.
Setiap kali ada penilaian hadiah, Pak Somad akan mengajukan pencalonan. Namun rezeki tidak menyebelahi Pak Somad. Malah dalam laporan penilaian, buku Pak Somad tidak pernah tersenarai di peringkat akhir. Pak Somad pernah terfikir adakah buku yang dihantar untuk pencalonan sampai pada urusetia atau dibuang dalam tong sampah. Namun, Pak Somad sentiasa bersangka baik.
“Tapi Pak Somad, ada juga buku-buku yang terbit sendiri menang hadiah. Yang penting, ada tahun terbit dan nombor ISBN. Siapa yang terbit itu tak penting,” Rahmatan menyatakan pandangannya.
“Itu penulis kayangan, Rahmatan! Ada ijazah. Ada master. Ada PhD. Ada gelaran yang gah-gah! Buku mereka akan dapat perhatian daripada penilai. Jadi, kalau Rahmatan nak jadi penulis, kena ada ijazah. Ijazah bidang apa pun tak kisah. Setidak-tidaknya, karya yang dihasilkan akan dipandang oleh pengkaji dan penilai,” ujar Pak Somad seolah-olah memberi nasihat kepada Rahmatan.
“Macam mana pula buku-buku cerpen Pak Somad? Ada menang hadiah?” Rahmatan mengumpan Pak Somad. Hari ini banyak cerita yang diluahkan Pak Somad. Inilah masanya Rahmatan ingin mengorek sebanyak mungkin.
Pak Somad menarik nafas. Dia menghirup air kopi yang masih bersisa. Rahmatan turut minum air kopi buatan Pak Somad.
“Aku ini penulis cerpen konvensional. Tulis cerita secara kronologi. Ada permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Cerpen konvensional ini susah mendapat tempat di hati editor akhbar dan majalah. Apatah lagi di hati para penilai. Pada mereka, cerpen konvensional sudah ketinggalan zaman,” terang Pak Somad panjang lebar.
“Habis itu, editor berminat cerpen yang macam mana, Pak Somad?” aju Rahmatan ingin tahu.
“Cerpen yang berbentuk absurd. Cerpen yang banyak menggunakan teori-teori sastera. Cerpen yang ceritanya mencabar pemikiran. Cerpen yang mengandungi falsafah. Kesemua itu memberi impak tinggi terhadap sastera tanah air,” ujar Pak Somad kemudian menyambung lagi.
“Sedangkan cerpen yang aku tulis hanya berkisar kisah realiti masyarakat. Kisah orang miskin, kisah orang kaya, kisah orang curi duit, kisah orang politik, dan macam-macam lagi lah. Yang aku paparkan, itulah realiti kehidupan manusia sekarang ini,” jelas Pak Somad tentang tujuan dia menulis.
“Teori sastera itu apa, Pak Somad?” Pertanyaan Rahmatan jelas menampakkan kedangkalan ilmunya tentang sastera.
“Teori sastera ni banyak, Rahmatan. Ada teori sastera barat. Ada teori sastera Melayu. Aku tak ambil kisah pasal teori sastera ni. Aku hanya ingin menulis dan bercerita. Cerita aku daripada realiti kehidupan manusia. Itu mesej yang ingin aku sampaikan kepada pembaca. Aku ni tak sekolah tinggi. Jadi, aku memang tak pandai berteori-teori ni,” ujar Pak Somad menyatakan pendiriannya.
“Pak Somad bagilah contoh teori sastera itu. Saya pun nak tau juga,” desak Rahmatan ingin juga tahu.
“Kalau tak silap ingatan akulah. Teori sastera Melayu itu teori takmilah, teori taabudiyyah, teori pengkaedahan Melayu. Teori sastera barat pula teori formalisme, teori strukturalisme, teori semiotik, teori semantik, teori stilistik, dan entah apa-apa lagi yang tik-tik!” ujar Pak Somad. Suaranya tersangkut-sangkut bila bibirnya melafazkan istilah teori sastera barat.
Mulut Rahmatan menganga besar. Pada Rahmatan, istilah-istilah yang disebut Pak Somad terlalu asing. Baru hari ini Rahmatan mendengar.
“Tapi Pak Somad, salah ke kita menulis cerpen konvensional? Pada sayalah, menulis itu ikut kemampuan dan kecenderungan seseorang penulis. Macam penulis almarhum Azizi Hj Abdullah. Cerpen dan novelnya semua ditulis gaya konvensional. Malah almarhum banyak memenangi hadiah sastera dan sayembara. Cuma ralatnya almarhum tidak dikurniakan anugerah sasterawan negara,” Rahmatan menyatakan pendapatnya.
“Haah! Kenal pun kau penulis Azizi. Itulah antara yang mengecewakan aku. Almarhum itu idola aku. Gaya penulisan cerpen-cerpen aku banyak terpengaruh dengan gaya Azizi. Almarhum memang layak menerima anugerah itu,” ulas Pak Somad.
“Saya tahu melalui pembacaan, Pak Somad,” akui Rahmatan.
“Bagus! Nak jadi penulis kena banyak membaca!” kata Pak Somad.
“Jadi, Pak Somad akan terus berkarya? Menulis puisi dan cerpen? Menerbitkan buku? Biarpun karya Pak Somad tak pernah menang hadiah? Biarpun nama Pak Somad tidak pernah mendapat perhatian pengkaji sastera?” tanya Rahmatan ingin mengetahui pendirian Pak Somad.
“Ye! Aku akan terus menulis selagi hayat dikandung badan. Aku tidak peduli pasal kelompok dalam sastera. Biarpun kelompok ini telah menjadi satu virus yang memang sudah lama ada dan diwarisi turun temurun. Aku tak peduli itu semua. Aku tetap akan menulis!” teriak Pak Somad secara tiba-tiba. Suara Pak Somad bergema di dalam rumahnya.
Rahmatan terkejut dengan aksi spontan Pak Somad. Rahmatan tidak bertanya lagi pada Pak Somad. Hari ini banyak perkara yang diketahui Rahmatan tentang diri Pak Somad seorang sasterawan yang tidak didendang.
Sewaktu Rahmatan keluar dari rumah Pak Somad, dia berhenti di tepi tong sampah. Sampul surat bersaiz A4 yang dipegang Rahmatan ditenungnya dengan mata lesu. Dalam sampul itu ada sejumlah puisi yang ingin diberi pada Pak Somad untuk disemak. Namun setelah dia mendengar dengan panjang lebar cerita Pak Somad, hati Rahmatan jadi hambar.
Serentak dengan kaki Rahmatan melangkah, serentak itu juga tangannya mencampakkan sampul surat itu ke dalam tong sampah. Hati Rahmatan terasa kosong dan hampa. – Mingguan Malaysia