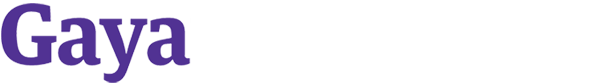DIA tetap dengan pendiriannya. Dia cuba pertahankan walau apa cara sekalipun. Tapi untuk menghamparkan tikar kebenaran, tidak sekali-kali. Biarlah apa orang nak kata. Biarlah mak ayah marah padanya, biarlah adik-beradiknya gelarkan dia keras kepala dan biarlah sepupu-sepapatnya nobatkan dia sombong, dia tidak kisah. Biar. Mereka berhak untuk kata apa sahaja. Dan dia juga berhak demi dirinya. Rahsia itu dia akan gengga hingga ke akhir hayat.
“Pergilah jenguk Pak Su. Dah sebulan dia tak bangun, hanya kamu saja yang belum sampai ke rumahnya.” Kata-kata mak melompat masuk ke lubang telinganya.
Dia tahu, mak masih lagi berada di muka pintu biliknya. Dia berpaling sambil membalikkan badannya. Dia lurutkan selimut yang bercorak belang-belang warna biru laut ke paras dada. Dia tumpahkan pandangannya ke kelopak mata mak dengan lembut. Dia bangun dan bersila di atas katil kayunya.
“Bukan Ikah tak mahu pergi mak, cuma Ikah sibuk. Esok Ikah kena ke sekolah. Ada mesyuarat dan juga gotong-royong. Mungkin tak sempat untuk Ikah pergi. Nantilah dulu.” Dia berbohong sekali lagi. Entah ke berapa kali dia harus berbuat demikian. Memang dia rasa bersalah, terutamanya dengan mak, tapi jendela hatinya belum terbuka untuk ke rumah Pak Su dan bertemu dengannya.
Pak Su tiba-tiba jatuh sakit. Lumpuh separuh badan. Dari pinggang ke bawah. Dan kedua-dua tangannya membengkak. Itu yang dia dengar daripada mak. Rumahnya dengan Pak Su hanya berselang lima buah. Pak Su tinggal di rumah pusaka arwah nenek.
Tapi hingga ke hari ini hanya dia seorang yang belum ziarah Pak Su. Hanya dia seorang belum menjejakkan kakinya ke rumah Pak Su yang dahulunya itulah tempat permainannya, tempat dia menghabiskan waktu petang-petangnya.
Sebelum arwah nenek meningga dunia, walaupun Ikah tidak betah untuk berada di situ, namun dia tetap hadirkan diri. Tapi dia cuba mengelak daripada bertembung dengan Pak Su.
Sehinggalah dia ditawarkan untuk meneruskan pengajiannya di China, dia berpeluang untuk menjauhkan diri daripada Pak Su. Dia merasakan takdir berpihak kepadanya. Dia bebas. Dia tidak perlu lagi berjumpa dengan Pak Su.
“Kenapa Kak Long izinkan Ikah ke sana. Jauh Kak Long, biarlah Ikah belajar di Malaysia saja. Kalau terjadi apa-apa, susah Kak Long.” Pak Su taburkan baja risau di perdu nubari maknya. Pak Su tidak mahu Ikah keluar dari negara kelahirannya.
Namun Ikah nekad, dia tetap akan pergi. Kalau masih ada tempat paling jauh lagi, dia tetap akan pergi. Dia pastikan gunung keyakinannya takkan ditarah dek jentolak pujuk rayu mak. Hinggakan mak terpaksa akur. Mak tiada daya untuk menolak kehendaknya. Hanya Pak Su yang menentangnya habis-habisan.
Hingga kini, semua kerabatnya beranggapan, dia tidak suka kepada Pak Su kerana hal ini. Biarlah dia dan Yang Satu saja tahu perkara sebenar.
Hampir semua penduduk kampung menjenguknya. Pak Su seorang pesara kerajaan. Semua orang mengenalinya. Pak Su amat disukai kerana sikapnya yang peramah dan suka bersedekah.
Musala di kampungnya, hampir separuh kos pembinaan tempat wuduk wanita yang baharu disumbangkan olehnya. Sakit demam penduduk kampung, Pak Su lah orang pertama yang hadir ziarah.
Sekiranya ada kematian, Pak Su juga yang ambil berat tentang pengurusan jenazah daripada awal hingga jenazah selamat dikebumikan. Tidak cukup dengan itu, kadang-kadang Pak Su memberi wang kepada keluarga si mati untuk mengadakan kenduri tahlil.
Pendek kata, Pak Su amat disenangi dan dihormati penduduk kampung. Di mata mereka, Pak Su adalah contoh yang patut diteladani.
Dia rebahkan badannya semula. Matanya tidak berkelip. Pandangannya terpaku ke jarum jam yang menunjukkan 11.50 malam.
Entahlah, malam ini terasa bagaikan turut sama berduka dengannya. Mutiara hujan yang berjatuhan di bumbung rumahnya berdetap-detup seperti hatinya yang pedih dibedil kenangan silam.
“Ikah tak nak mandi Pak Su. Ikah nak mandi di rumah mak.” Dia yang berusia enam tahun ketika itu hanya mampu menolak.
Pak Su tetap mandikannya. Pak Su gosok badannya dengan sabun. Pak Su ratakan air ke seluruh tubuhnya. Pak Su sentuh setiap inci tubuh badannya. Ada bahagian tertentu, Pak Su pegang lama-lama. Ikah tak suka. Ikah geram. Ikah benci Pak Su.
Hingga ke hari ini kenangan itu bergentayangan di minda fikirnya. Tertugu teguh di dataran ingatan. Bukan sekali Pak Su melakukannya. Yang dia ingat lebih daripada tiga kali. Dia cuba bunuh kisah silamnya itu. Semakin dilupakan semakin kuat melekat di dinding fikirnya. Bilah-bilah tajam peristiwa itu sering meracik ingatan sehingga robek ketenangannya.
Dahulu, dia hanya tidak suka dengan perbuatan Pak Su. Apabila dia memasuki sekolah menengah, barulah dia tahu, bahawa dia telah diperlecehkan bapa saudara sendiri.
Dia dicabul! Dia rasakan seolah-olah harga dirinya dipijak-pijak, diinjak-injak bahkan dinodai dengan rakus. Itupun oleh saudara terdekat sendiri. Bukan orang lain.
Ikah perlahan-lahan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Dia rapatkan tirai kelopak mata. Dia berharap nyanyian unggas yang memecah keheningan di malam itu tidak mengganggu tidurnya yang hanya berbaki beberapa jam sahaja.
Pagi itu Ikah yang tinggi lampai tubuhnya bersiap untuk ke sekolah. Dia yang mengajar bahasa Mandarin di sekolah berasrama penuh tergesa-gesa mengambil sarapan nasi goreng ikan masin yang disediakannya sendiri.
“Balik sekolah nanti, kita ke rumah Pak Su ya Ikah.” Kata-kata mak menerjah gegendang telinganya. Suapannya terhenti. Ikah merenung cawan kopi berwarna putih di hadapannya. Dunianya tiba-tiba terasa gelap, hitam seperti kopi yang dibancuhnya. Bagaimana harus dia mengelak lagi.
Sepanjang perjalanannya ke sekolah, hatinya tebal berdebu gelisah. Kali ini dia memang tidak boleh menolak lagi. Dia mesti hadapinya. Dia mesti berdepan dengan Pak Su.
Dia akan ceritakan kepada mak, dia akan jelaskan kepada adik-beradiknya dan dia akan khabarkan kepada sepupu-sepupunya iaitu anak-anak Pak Su.
Dia akan luahkan segala-galanya. Biar semua tahu. Dia tidak ingin berahsia lagi. Dia akan pacakkan tiang keadilan untuk dirinya sendiri.
“Ikah, saya sudah kumpulkan murid-murid di dalam dewan. Nanti kita sama-sama bagi taklimat gotong-royong.”
Suara Arif menyambutnya sebaik dia tiba di bilik guru. Guru Bahasa Melayu yang tegap dan berkumis nipis itu sering membantunya dalam hal yang berkait dengan program sekolah.
Arif juga menjadi mangsa traumanya. Hampir lima tahun Arif menunggu jawapan. Menunggu persetujuan daripadanya.
Bukan dia tidak suka kepada Arif. Dia memang suka. Cuma dia terganggu dengan peristiwa yang menimpanya.
Arif tidak putus-putus memujuk dia untuk terima lamarannya. Dia bukan menolak, dia hanya belum bersedia. Itu sahaja. Dia yakin Arif adalah yang terbaik untuknya. Cuma belum tiba masanya.
Kali pertama Arif menjejakkan kaki ke sekolah, dia seorang yang pendiam dan tidak bergaul dengan rakan guru yang lain. Rupa-rupanya Arif juga mempunyai sejarah hitam yang sukar untuk dia lupakan.
Perempuan yang menjadi tunangannya selama setahun mati akibat dirogol dan dibunuh secara kejam. Kisah pembunuhannya memang tular di media masa. Dan Ikah sendiri pun tahu mengenai kejadian tersebut.
Lama-kelamaan dia dan Arif semakin akrab. Dan tanpa berbasa-basi Arif luahkan perasaannya. Arif ingin melakar kisah hidup bersamanya. Arif setia menunggu sampai bila pun. Sehingga dia bersedia.
Dia melangkah perlahan-lahan ke atas rumah Pak Su. Bunyi papan lantai berderit, setiap kali dia menapak.
Dan Ikah masih ingat lagi, lantai inilah yang menjadi saksi setiap kali Pak Su berbuat tidak baik kepadanya. Dia akan berlari pulang ke rumah.
Hentakan kakinya sering ditegur arwah nenek. Dia tidak peduli. Dia ingin cepat tiba ke rumahnya. Dia ingin mandi semula, dia tak nak bekas sentuhan Pak Su melekat di badannya. Dia guna sabun banyak-banyak, dia gosok badannya berkali-kali. Biar hilang semua, sentuhan, sakit dan rasa marahnya kepada Pak Su.
Semua mata memandang Ikah. Mak Su yang berada di ruang tamu memandangnya dengan pandangan yang paling sayu. Dua sepupu perempuannya yang berusia 18 dan 20 tahun hanya berbalas pandangan, saling tersenyum. Dia membuang senyum yang hambar kepada mereka berdua.
Ikah melihat Pak Su yang terbaring di atas katil kayu di balik pintu yang tergelohong. Dia mendekati Pak Su.
Dia bersila di birai katil Pak Su. Bau minyak urut mencucuk-cucuk lubang hidungnya. Mangkuk kecil yang diletakkan minyak urut, Ikah tolak masuk ke bawah katil.
Dia hantarkan pandangannya ke wajah Pak Su yang cengkung dan tidak bermaya. Dia perhati tubuh Pak Su yang kurus dan keding.
Pak Su memandangnya dengan renungan yang penuh makna. Mulut Pak Su menggelugut. Dia tahu Pak Su ingin berbicara dengannya.
Mak Su selak kain selimut nipis yang menutupi badan Pak Su. Mak Su tunjukkan kedua-dua belah tangan Pak Su yang bengkak. Mak Su tidak tahu apa penyakit Pak Su.
Hospital pun tidak dapat mengetahui punca tangan Pak Su jadi begitu. Kelima-lima jari tangan Pak Su bincul hingga tidak nampak bentuk bukunya. Ikah melihat jari-jemari Pak Su seperti lima batang kayu yang sama saiz disusun berbaris.
Ikah tidak sampai hati melihat Pak Su berkeadaan begitu. Cepu hati Ikah tiba-tiba penuh terisi simpati. Ikah pasrah. Ikah pujuk hatinya untuk maafkan Pak Su.
Mungkin Pak Su telah berubah setelah sekian lama. Sebab setiap kali Ikah berjumpa Pak Su, Pak Su seolah-olah tidak ada kesalahan dengannya. Pak Su bagaikan lupa tingkah tidak bermoral kepadanya.
Mungkin 24 tahun lepas Pak Su tidak mampu memerangi nafsunya sendiri. Pak Su kalah, hingga sanggup melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Ikah.
Ikah yakin, Allah Maha Adil dan Saksama. Biar Dia yang tentukannya. Ikah ingin maafkan kesilapan Pak Su yang sekian lama menjerut resahnya.
Ikah akan minta dengan-Nya untuk lembutkan hatinya, lenturkan amarahnya dan kendurkan kelukaan yang terpendam sekian lama.
Tiba-tiba Ikah teringat seseorang yang sekian lama menunggunya. – Mingguan Malaysia