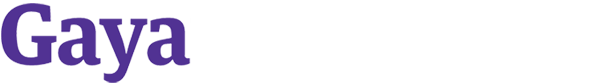Hembusan lembut bayu Pantai Morib mengibar-ngibarkan hujung tudung bercorak abstrak yang dipakai. Namun, nyamannya tidak mampu mendamaikan kolam hati yang kencang berkocak.
“Abang nak anak kita sendiri.” Isu anak angkat yang disarankan isterinya, Faridah, untuk kesekian kali ditolak mentah. “Buat sajalah pembedahan itu, bukan ke doktor dah terangkan risiko untuk berjaya tinggi.” Dia tahu benar jiwa Faridah, kalau keras pun, hanya sekeras kerak nasi. Dipujuk, lembutlah ia.
Faridah akur. Putih kata Zaidi, putihlah. Faridah menyulam taat. Semakin hampir dengan tarikh pembedahan, debar di hatinya kian memuncak. Ini bukan kali pertama dia melaluinya, tetapi dia tidak mengerti, mengapa bolak balik hatinya menggebu saban hampirnya waktu. Jiwanya dicengkam ragu!
Hari dirancang kunjung tiba. Hari yang dia tidak menyangka, aturan Tuhan untuknya tertulis hiba. Tepat pukul 8 pagi, Faridah ditolak masuk ke bilik pembedahan. Renungan sayu berlabuh di matanya seakan menghantar lambaian perpisahan buat mereka. “Astaghfirullahal’azim.” Lafaznya berulang kali seraya matanya menancap lelangit hospital berona putih bersih, persis warna kain kapan. Faridah mengulang-ulang saiyidul istighfar semasa proses bius dilakukan. Dia sedar, tidak ada pergantungan terbaik melainkan hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Berkuasa menghidup dan mematikan segala sesuatu. Tidak lama, zikirnya diam bersama jasad yang pegun.
Kopi panas di tangan disisip perlahan. Bihun goreng kantin hospital yang terhidang di depannya sekadar dipandang sepi. Hati Zaidi menyertai Faridah, isteri yang sangat dicintainya, biar pun diduga lapan tahun usia pernikahan, mereka masih belum direzekikan dengan anak.
“Carilah pucuk muda, senang lekat,” usik Hamidun, teman lepaknya di kedai mamak. Ketawanya berdekah-dekah itu kemudian tercantas. “Aku sayangkan Faridah. Dia isteri dan juga sahabat yang sanggup susah senang bersama. Daripada naik motor cabuk, rumah sewa yang kosong tiada apa, makan nasi berlauk telur sahaja, dan lebih dahsyat, pernah kami jamah biskut kering selama dua ke tiga hari sementara nak tunggu gaji, tapi dia tak pernah merungut. Tak pernah!” Kata-kata Zaidi menancap ke jantung Hamidun!
“Dengan kereta mewah yang aku pakai sekarang ini memang tak susah nak cari perempuan. Tapi, aku nak isteri yang boleh cintai aku di saat aku tak punya apa. Kau fahamkan?” Sejak itu, usul bernikah lagi dikuburkan. Hamidun sependapat dengan sahabatnya itu. Wanita sebaik Faridah sukar ditemui. Dia mengeluh mengenangkan nasib diri yang masih bujang.
Kring! Kring!
Telefon bimbitnya berdering. Tergesa-gesa Zaidi menyeluk poket seluar, bimbang jika panggilan itu datangnya dari bilik pembedahan. Jantungnya berdegup kencang. “Oh, emak!” Zaidi menangguk-angguk. Pesan berbakul-bakul dari emaknya itu berbalas anggukan. “Kau dengar ‘tak emak cakap ini, Zaidi? Selesai pembedahan jangan lupa telefon emak,” pesan emak sebelum diputuskan panggilan lain yang masuk.
“Ya Allah!” Jantung Zaidi berombak keras. Bergegas dia berkejar ke bilik pembedahan. Renungan Faridah tiga jam lalu mengetuk-ngetuk kepalanya. Zaidi gementar memikirkan kemungkinan paling ditakutinya.
“Encik Zaidi, minta tandatangan di sini,” ujar doktor Ariani, antara pasukan perubatan yang melakukan pembedahan ke atas isteri kesayangannya. Wajah Zaidi basah. Terbang semua rasa malunya sebagai lelaki di depan doktor Ariani dan doktor Tay, yang bertugas memberi penerangan kepadanya berkaitan komplikasi dihadapi isterinya ketika itu. “Tolong doktor, selamatkan isteri saya. Dia nyawa saya, doktor.” Jiwanya terbang menemani si isteri yang sedang bergelut untuk diselamatkan. Terketar-ketar tangannya menurunkan persetujuan pada kertas putih itu. “Maafkan abang, sayang…” Terhenjut-henjut tubuhnya menangis sambil menahan kepedihan. “Jangan tinggalkan abang!” Putaran dunia seolah-olah terpaku. Zaidi hanyut dan lemas dalam kedukaan.
Pandangannya memegang erat pintu bilik pembedahan itu sejak sejam lalu. Harapan yang disemai di balik pintu, sungguh mencemaskan hatinya. Zaidi menginginkan cahaya itu kembali dalam hidupnya. Sebaik cahaya lampu di luar bilik pembedahan itu padam, muncul sepasukan doktor dengan wajah lelah beserta riak muka yang sukar ditelah.
“Sodaqallahul’azhim.” Zaidi menutup naskhah al-Quran yang dibacanya. Dua bulan menemani Faridah yang terlantar koma, telah dua kali dia khatam bacaan al-Quran. Sesuatu yang di luar kebiasaannya. Sebelum ini, hubungannya dengan kalamullah yang mulia itu tidak begitu rapat. Ada hari dia membacanya, ada kala dia lupa atau dilupakan dek kesibukan bekerja. Mungkin ini antara hikmah mengapa Allah mendiamkan Faridah kaku di pembaringan. Lumrah manusia, bila susah akan mencari-cari Tuhan. Apabila derita akan memanggil-manggil nama Tuhan.
“Bang, kalaulah aku terima usul Faridah ambil anak angkat, dia tak perlu koma macam ini. Aku kejam bang! Aku terlalu pentingkan untuk dapat zuriat sendiri.” Zaidi mengongoi bagai anak kecil di depan Malik, abang kandung Faridah, yang datang berziarah petang semalam.
Malik menepuk-nepuk bahu Zaidi. “Jangan melawan takdir. Ini rencana Allah. Banyakkan beristighfar. Jangan disebut lagi perkataan ‘kalau’ itu. Sebagai orang yang beriman, kita reda atas qada dan qadar Allah,” nasihat Malik.
“Allah uji tandanya sayang. Allah uji sebab nak bagi rahmat kepada kamu berdua.”
BELAJARLAH REDA
Beberapa rakan usrah isterinya berkunjung ziarah tengah hari itu. Zaidi memberi ruang kepada mereka dengan berganjak ke sudut tepi bilik. Bergilir-gilir mereka memeluk, mencium, dan berbisik ke telinga Faridah. Mungkin memberi kata-kata semangat, Zaidi membuat andaian. Doktor memang menyarankan untuk terus menyuntik kekuatan semangat kepada Faridah, agar membantu jiwanya kuat dan bangkit daripada koma dengan izin Allah. Zaidi sesekali membuang pandang kepada perlakuan mereka terhadap isterinya yang kaku. Ya, tiada satu pun tindak balas daripada Faridah sejak disahkan koma.
Sejak itu jugalah dirinya tidak lagi terurus. Jambang di wajahnya sudah lama tidak dirapikan. Hidupnya selama dua bulan ini dihabiskan menemani sekujur jasad yang bernyawa tetapi tidak lagi bergerak. Makannya pun sekadar mengalas perut. Wajahnya sama cengkung seperti Faridah. Pakainya diurus oleh Malik dan isterinya, yang beberapa hari sekali berkunjung membawa pulang baju kotor dan membawakan pakaian bersih. Perniagaannya turut diserahkan bulat-bulat kepada Malik untuk menguruskannya. Mujur ada abang iparnya.
Zaidi memerhati perlakuan kak Asma terhadap Faridah. Lama dia bercakap-cakap di telinga Faridah, matanya pun turut merah membasah. Zaidi tidak dapat menangkap butir bicaranya yang perlahan itu.
Tak semena-mena, Zaidi perasan butiran jernih melorot dari tepi mata Faridah. Zaidi mendekat untuk memastikannya. Faridah menangis! Benar, isterinya menangis! Itulah respon pertama Faridah sejak mengalami koma. Zaidi berkejar memanggil doktor.
“Faridah!” Malik memanggil seraya melangkah masuk ke bilik itu. Nafasnya mencungap-cungap setelah berlari-lari anak. Sebaik dikhabarkan Faridah telah sedar daripada koma, berita itu satu rahmat buatnya.
Tak lama selepas menerima berita gembira itu, belum sempat dia menyelesaikan urusan kerjanya untuk mengunjungi Faridah, Zaidi menghubunginya buat kali kedua dengan khabar mencemaskan! Langkah dan suara Malik terpaku di muka pintu. Zaidi duduk tersandar di dinding dengan mukanya ditelungkupkan mencium lutut. Gerak badannya terhinggut-hinggut.
Mata Malik memandang tubuh yang berselubung di atas katil. Longlai. Perlahan-lahan Malik menyelak selimut putih itu. “Faridah…” Air mata jantannya pecah berkecai!
Usai pengebumian, Zaidi berteleku di sisi kubur. Kesan air mata telah kering. Cuma bengkak matanya jelas ketara. “Sabar, Zaidi. Marilah pulang.” Zaidi menggeleng. “Abang baliklah dulu.”
Malik duduk di sisi adik iparnya, memanggul rasa yang sama. Kehilangan. Cuma luka di hati Zaidi pastilah lebih dalam. Faridah isteri kecintaannya dan teman hidupnya. Di saat mereka berjanji bersama melakar indahnya pelangi, Faridah langsung pergi meninggalkannya sendiri.
“Dia sempat sedar untuk beritahu yang dia telah pun reda dengan qada dan qadar Allah yang tertulis buat kami, bang. Dan kami sama-sama berjanji untuk serahkan segala urusan kami kepada Allah.”
“Alhamdulillah. Faridah pergi dalam tenang dan hatinya reda dengan kehendak Allah. Moga syurga buatnya,” nasihat Malik sambil menepuk-nepuk bahu Zaidi. “Aku reda, bang. Allah nak bagi dia syurga dahulu. Aku akan menyusul nanti.” Zaidi memasang tekad.
“Nak buat apa beras berkampit-kampit ini, Zaidi?” Malik hairan. Dia mengira-ngira, adalah dalam 40 kampit, penuh dalam bonet dan atas kerusi dalam kereta. Zaidi baru pulang dari pasar raya selepas majlis pengebumian tadi. “Nak bayar fidyah, bang. Kalau-kalau ada puasa Faridah belum diganti. Nanti abang tolong edarkan beras ini ya?”
“Iyalah. Eh, kau nak ikut abang ke masjid tak?” “Ya bang, naik motor saja lah. Cepat sikit.” Zaidi membonceng di belakang. “Bang, kunci kereta aku gantung di dinding.” Bukankah mereka akan pergi bersama-sama edarkan beras itu? Malik berasa pelik.
“Allah…!” Motor yang dinaiki mereka hilang kawalan dan terperosok ke dalam longkang demi mengelak seekor babi hutan yang menerpa ke laluan mereka.
“Nanti abang tolong aku edarkan beras-beras ini ya? Bang, kunci kereta aku gantung di dinding.” Mata Malik merah. Semalam Faridah, hari ini Zaidi pula menyusul. Malik menatap kubur mereka yang bersebelahan seolah berjanji untuk bersemadi bersama.
Malik cemburu. Mereka pergi dengan cinta kepada Allah. Mereka pergi dalam keadaan telah menyerahkan semua urusan kepada Allah. “Nantikan abang…” bisik Malik. Enjin kereta Zaidi dihidupkan. Dia melangsungkan amanah ditinggalkan. Luka-luka kecil pada tubuhnya langsung tidak terasa. – Mingguan Malaysia