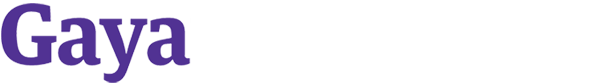Karya ROZAINI ABDULLAH
DIA memegang betis kiri dan menggosok-gosoknya dengan tapak tangan. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Berulang. Sekali, dua kali, tiga kali. Namun denyut di kaki tidak juga berkurangan.
Berkerut muka menahan sakit. Hendak diurut di tempatnya, terasa nyeri lantaran bengkak makin membusut. Dia letakkan jari telunjuk dan tekan perlahan-lahan. Memang sakit!
‘Esok, lusa, harap-harap surut nanti.’ Kesal mendakap hati. Sesal tidak mendengar kata-kata Senah, isterinya.
Pagi itu, dia ingin memangkas dahan rambutan gading yang berada betul-betul di hadapan rumah. Buah lebat dan hujung dahan yang menggelepai ke bawah, menyentuh bumbung kereta Wira kelabunya yang berusia 20 tahun.
Dia berdiri di atas pangkin yang berada di bawah pokok dan tangannya berpegang pada satu dahan. Dia bercadang untuk berpijak di dahan lain, senang untuk cantas hujungnya. Entah kenapa tangan kirinya terlepas pautan, tak sempat dia imbangkan badan.
“Gedebuk,’ dia jatuh dan kakinya terpelecok, lantas terkena pangkin yang bangsai hujungnya. Terasa serpihan kecil kayu menusuk pedih di bawah buku lalinya.
“Itulah, saya dah cakap, awak tu semua nak buat sendiri. Kan senang kalau upah orang pangkaskan dahan-dahan itu.” Dia pekakkan telinga. Suara Senah menggerutus bagai buluh diperun.
‘Ah, perempuan memang macam itu, tak habis-habis berleter, bukannya nak tolong!’ Suara di dasar fikirnya perlahan-lahan tenggelam dek kesakitan yang mencengkam. Terjengkit-jengkit dia dan Senah berjalan menuju ke beranda rumah.
“Payah nak nasihatkan orang tua ini. Kata dia saja yang betul”. Roda bebelan Senah hanya berputar di dalam hatinya sahaja.
Dia kenal suaminya. Lelaki yang seluruh kepalanya memutih itu telah bersamanya hampir 50 tahun. Senah tahu fiilnya yang keras kepala. Dari muda sampai ke tua. Bercakap dengannya bagai memandikan itik yang tidak basah. Orang lain semua salah. Hanya dia yang betul. Apa sahaja yang keluar dari mulutnya, orang lain mesti akur. Keputusannya muktamad. Noktah. Tiada siapa boleh bantah.
Dek kedegilannya itulah, dia kini bergantung dengan tongkat kayu untuk mengatur langkah.
Lalang tegarnya makin menjulang apabila dia tidak mahu ke klinik, mengubat kakinya yang mula menampakkan nanah. Berbuih mulut Senah menasihati. Senah yang bertubuh kecil dan kurus, bimbang andai lukanya semakin memborat. Pun begitu, dia tetap dengan keras kepalanya.
Dia yakin kakinya pasti pulih. Beberapa serpihan kayu kecil yang menusuk kakinya telah dikeluarkan. Setiap hari kakinya dilumur dengan daun kapal terbang yang diramas hingga mengeluarkan lendir. Itulah yang dilakukannya setiap kali dia mengalami luka-luka.
Dia membelingas ke sekeliling rumah. Di sebelah kanan, rambutan Che Embong sebanyak tujuh pohon berselang dengan Anak Sekolah sebanyak enam pokok, lentur hujung dahannya, menunduk ke bumi dek lebatnya buah.
Tiga pohon rambutan gading menguning meneduhi laman hadapan rumah manakala di sebelah kirinya berbaris pohon dokong, duku dan rambai. Bertangkai-tangkai, bergugus-gugus mendakap dahan dan batangnya. Lebat. Lebat sangat. Manggis pula berjatuhan di tanah tanpa ada yang mengutipnya. Ranumnya hanya untuk menunggu gugur dan menjadi baja tanah!
Durian Tok Litok sebanyak lima pohon megah berdiri di belakang rumah. Sekarang musimnya telah habis.
Bara kesal perlahan-lahan membakar nubarinya. Angkara virus Korona yang tak berkesudahan inilah, sudah sekian lama dia tidak bertemu dengan dua orang anak dan cucu-cucunya yang bermastautin di luar Tanah Serendah Sekebun Bunga.
Terkadang dia cuba menyalahkan kerajaan. Entah berapa kali tali harapannya terputus. Seperti menunggu buah yang tidak gugur!
Buah durian yang disimpan untuk mereka semuanya sudah jadi tempoyak dan lempuk. Salak yang dikutip setiap hari juga akhirnya buruk di dalam raga.
Terkadang Senah lontarkan bola ketidakpuasan hati kepadanya.
“Orang datang nak beli, awak tak nak jual. Anak cucu kita entah bila dapat balik kampung. Daripada buah itu busuk dan gugur, sekurang-kurangnya dapat juga hasil, kalau dibeli orang.” Senah tahu, butir bicaranya ibarat mencurah air ke daun keladi.
Memang dari dulu lagi, dia menanam pokok buah-buahan bukan untuk dijual, sebaliknya untuk dinikmati anak cucu dan saudara mara yang datang berkunjung.
“Hmm…bilakah agaknya mereka dapat pulang?” Benih-benih kecewa mula bercambah dan tumbuh subur di batas hatinya.
Dia teringat cucu-cucu lelaki yang sangat gemar memakan buah durian. Setiap pagi mereka selalu mengikutnya ke belakang rumah untuk mengutip buah gugur. Dan di atas pangkin itulah mereka mengopek buahnya.
Bagai terngiang-ngiang di telinga, suara cucu-cucu perempuan yang menjerit dan menangis setiap kali pacat bertamu di kaki dan betis mereka.
Dia membunuhnya dengan menggunakan cecair peluntur yang dicelup batang kayu kecil. Sebaik diacukan kepada pacat, mengeliang geliut badannya sebelum jatuh ke tanah. Namun mereka tidak pernah serik menemaninya mengutip dokong, duku dan salak.
Terbayang kelibat anak dan menantunya yang meretus rambutan dan manggis dari pokok, dan buah yang agak tinggi sedikit diranggah dengan batang penyapu. Tak jemu-jemu mereka menikmatinya.
Ladang hatinya disembur racun rindu. Dia rindukan suasana itu. Dia rindukan waktu itu. Waktu musim buah bersama-sama anak, menantu dan cucu. Perih di kakinya tidak seberapa jika dibandingkan dengan perit menanggung kemarau rindu.
Perlahan-lahan dia menuju ke pangkin. Dia tepis beberapa helai daun kering dengan tangan kanan. Tangan kirinya memegang tongkat, menahan kaki kiri yang tidak berdaya berdiri dengan sendiri. Dia labuhkan punggung di tengah-tengah pangkin kayu. Dia menghela nafas. Panjang. Sekali lagi dia pandang ke kanan. Che Embong dan Anak Sekolah telah bertukar merah kehitaman. Malah ada yang gugur.
Pandangan matanya tiba-tiba ditarik rimbunan salak yang berbaris memagari halaman rumah dan kebunnya. Lebih 100 pohon semuanya. Buah-buahnya sudah tidak kelihatan lagi. Dia bangkit perlahan-lahan. Kecok kakinya walaupun bertongkat. Dia ingin melihat kalau-kalau salak, masih ada yang bersisa. Mungkin bersembunyi di balik pelepah dan batang.
Seperti direnjat elektrik, dia terkejut. Ibu jari kaki kanannya terpijak sesuatu yang menyakitkan. Dia tidak dapat mengimbanginya. Dia rebah. Kepalanya terantuk tunggul rambutan tua. Terasa suasana di sekelilingnya mula kelam. Makin lama makin gelita.
Tirai kelopak matanya disingkap perlahan. Dia mengambil masa dan pejam celik beberapa kali. Dia tahu, dirinya sudah berada di tempat yang paling tidak disukainya. Dia memandang ruang yang serba putih itu. Mencari Senah. Di manakah Senah? Dia cuba tegakkan kepala, lurus seiring sorotan mata, ke arah kedua-dua belah kakinya. Satu berbungkus penuh dan satu lagi berbalut di bahagian ibu jari.
“Kaki pak cik tercucuk duri salak, tembus ibu jari. Dan kaki sebelah lagi kami cuci nanah yang ada, sudah terkena jangkitan kuman, kerana tidak dirawat dari awal.” Muncul doktor di birai katilnya. Dia terdiam. Telinganya terus-terusan diterjah kata-kata doktor yang kesal dengan sikap sambil lewanya. Dia tahu, memang salah dia. Dan yang paling menggerunkannya, dia disahkan mengidap kencing manis.
Dia keseorangan. Tiada Senah di sisi. Senah tidak dapat menemani. Sudah hampir separuh purnama dia berada di sini. Hanya kesunyian yang masih erat bersamanya.
Ibu jari kaki kanannya tidak dapat diselamatkan dan terpaksa dipotong. Duri salaknya memakan tuan. Padahal setiap kali dia membuang daun salak yang tua, dia memastikan pelepah berduri dikumpul setempat dan tidak dibuang merata. Apakan daya. dia kena akur gerah yang tak dapat dielakkan, dia reda.
Kadang-kadang jemu mengikat dirinya hingga dia lemas. Mana tidaknya, dia seorang yang tidak pernah duduk diam. Ada sahaja pekerjaan yang dilakukannya ketika berada di rumah. Dia dijerat bosan. Pergerakannya juga terbatas. Mujur ada jururawat lelaki yang setia dan sedia membantu.
Dan yang paling dia sedih, hari dia dimasukkan ke wad, dikhabarkan, anak sulung, menantu dan seorang cucunya positif Covid-19. Dengan terlantarnya dia di hospital, sepatutnya mereka berpeluang untuk pulang ke kampung. Namun takdir mengatasi segala. Anak kedua juga terpaksa korbankan kepulangannya untuk menjaga kebajikan anak saudara yang tidak terpalit dengan virus Korona itu. Tiba-tiba hujan resah, lebat membasahi dan memenuhi kolam dadanya.
Kalaulah dia dengar nasihat Senah, pasti tidak jadi seperti ini. Pasti dia berada di rumah sekarang. Menjaga pokok buah-buahannya. Barangkali bermaharajalela monyet dan tupai, kerana dia tiada untuk menakutkan mereka. Sesekali babi hutan turut menyondol kebunnya.
Dia bukan kedekut untuk berkongsi rezeki, cuma dia geram setiap kali haiwan-haiwan itu menyerang. Pasti berantakan, bersepah dan paling dia benci, buah yang belum masak habis dikerjakan sebelum sempat ranum sepenuhnya.
Dia memejamkan mata. Tiada lain yang boleh dilakukan selain acap berbaring di katilnya. Dia teringat Senah. Senah tidak pernah datang menjenguknya.
Dia tidak menyalahkan wanita yang tujuh tahun lebih muda usia daripadanya itu. Dia tahu Senah tidak boleh memandu kereta sendiri dan Senah tidak pernah pergi ke mana-mana tanpa dia menemani. Dia akur, cukuplah sekadar mereka berhubung melalui telefon bimbit sahaja.
Hari ini dia dibenarkan pulang. Senah meminta bantuan anak jirannya Semail untuk menjemputnya di hospital. Hampir satu purnama dia meninggalkan rumahnya.
Sebaik sahaja kereta memasuki halaman rumah, matanya melilau melihat pokok buah-buahannya. Masih ada lagi beberapa pokok rambutan yang tersisa buah di hujung dahan. Semuanya merah darah ikan dan lebih daripada ranum.
Senah bergegas menyambutnya, Semail mengeluarkan kerusi roda untuk dia. Didorongnya hingga rapat ke beranda rumah. Dia ingin berada di situ untuk seketika. Dia memerhati sekelilingnya. Musim buah hampir habis. Manggis sudah tidak kelihatan langsung. Rambai masih ada dan kukuh berpaut di dahannya.
Keasyikannya lantas terganggu dengan deruman kereta yang memasuki pekarangan rumah. Dia berpaling. Dua buah kereta yang cukup dikenalinya perlahan-lahan parkir di bawah pohon rambutan gading.
Senah mendugas mendapatkan mereka sambil menyebut nama-nama yang sudah lama dia tidak mendengarnya.
Itulah kemeriahan yang ditunggu-tunggu selama ini. Akhirnya senyuman Pak Nik Ali mekar dan berkembang. Tangkai rindunya telah terlerai. – Mingguan Malaysia