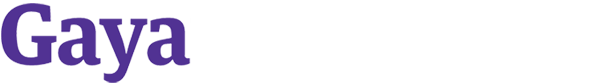Karya Umi Solehah
Dua minggu lepas, aku mendapat undangan ke majlis perkahwinan Encik Sulaiman, seorang berbangsa Pakistan yang menyewa di banglo dua tingkat berhadapan dengan rumahku. Agak lama Sulaiman sekeluarga menjadi jiran kami. Lebih kurang hampir dua tahun. Sempatlah juga kami merasai makanan asli orang Pakistan. Masih teringat sedapnya nasi biryani dan kambing perap bakar. Terasa rempah ratusnya sampai ke tulang kambing.
Anak-anaknya seramai enam orang. Lima orang lelaki dan seorang perempuan. Sumirah, gadis Pakistan bermata biru, satu-satunya anak perempuan tunggal Sulaiman. Keluarga Sulaiman sangat menjaga hukum-hakam agama Islam. Golongan wanita tidak dibenarkan keluar rumah sama sekali tanpa suami atau mahram mereka.
Mereka agak rapat dengan keluargaku. Seperti biasa, orang Pakistan yang datang ke Malaysia akan memonopoli perniagaan karpet, kain dan alatan elektrik. Semuanya dilaksanakan secara hutang. Strategi yang mampu mencairkan hati orang Melayu untuk menjadi pelanggan setia peniaga Pakistan.
Biarpun harganya berlipat kali ganda tapi pujuk rayu bayaran ansuran dan ‘ikut suka adik manis’ menyebabkan barangan penjual Pakistan sentiasa mendapat sambutan.
Atas beberapa masalah, mereka sekeluarga berpindah ke kawasan lain. Hinggalah dua minggu lepas, anaknya yang kedua, Mustafa datang menjemput kami untuk meraikan majlis perkahwinan abang sulungnya, Abdul Rahman. Terima kasih atas jemputan. Teruja sungguh aku untuk melihat cara perkahwinan orang Pakistan secara dekat.
Pada tarikh yang ditetapkan, aku ke rumah Encik Sulaiman. Sepasang baju kurung batik berwarna biji kundang menjadi pilihan. Solekan polos sahaja dan aku rasa bangga untuk menunjukkan hasil seni orang Melayu pada kaum kerabat Sulaiman yang didatangkan khas dari Pakistan.
Ketibaan aku disambut dengan gembira oleh keluarganya. Terasa seolah aku bukan berada di Malaysia. Negaraku sudah dijajahkah? Melihat ke luar rumah, bukan calang-calang kereta yang menjalar di hadapan rumah.
“Mesti Sulaiman ini asalnya orang kaya di Pakistan,” bisik hati kecilku.
“Sila naik, jangan malu-malu kakak, sebelah sini untuk orang perempuan,” kata isterinya, Fatimah, sambil memimpin tangan aku ke ruangan yang berbeza. Aku menjeling, rupanya tetamu lelaki dan wanita diasingkan.
Aku dibawa ke bilik khusus untuk orang perempuan. Sewaktu berjalan, aku sempat menjeling ke bilik di sebelah kiriku. Bilik itu dipenuhi dengan kertas yang dipotong kecil, debu seperti gandum, belon dan beberapa barang lagi yang berwarna-warni. Terpaku seketika aku melihat bilik tersebut. Menyedari keadaan yang agak pelik, Fatimah membawa aku masuk ke bilik tersebut.
“Kakak, di sini kaum perempuan akan menari dan menyanyi lagu budaya Pashtun. Jangan risau kakak, semasa menyanyi dan menari, kaum lelaki tidak bersama dengan kami,” jelas Fatimah. Mungkin dia tidak mahu aku rasa wasangka pada keluarganya.
“Itu semua, kertas, debu dan belon berwarna-warni kami taburkan semasa menari, sekurang-kurangnya walau jauh dari Pakistan tapi majlis kami tetap dengan budaya kami,” terang Fatimah lagi.
“Hebat juga jati diri orang Pakistan,” kataku di dalam hati.
“Mana pengantin?” tanya aku.
“Pengantin masih di dalam bilik, mari saya tunjukkan,” kata Fatimah. Aku dibawa ke bilik pengantin.
Terpana aku melihat kecantikan menantu Encik Sulaiman dan Fatimah. Bermata biru, hidung bak seludang, putih dan wajahnya menunjukkan usia yang sangat muda.
“Dia masih belajar, tapi bapanya suruh berhenti belajar untuk kahwin dengan anak saya,” jelas Fatimah.
“Dia setuju?”soalku.
“Mestilah kakak. Anak perempuan Pakistan sangat patuh pada mak ayah mereka,” jelas Fatimah lagi.
“Mari makan,” jemput Fatimah.
Aku dihidangkan dengan nasi Arab. Tiba-tiba perut terasa lapar yang amat sangat. Ketika sedang ralit menyuapkan nasi Arab, datang seorang perempuan Melayu duduk di sebelahku sambil tersenyum.
“Sila makan kak, ini resipi nasi Arab yang dibuat oleh suami saya. Sedap tak?” becok mulut dia bertanya sambil mencedok nasi ke pinggannya.
“Mana suami awak? Hebat betul air tangan suami awak, sampai orang Pakistan pun tempah dengan suami awak,” aku berseloroh.
“Itu suami saya, yang duduk di hujung sekali atas sofa, pakai kurta warna kelabu,” jelas perempuan muda itu sambil mengambil daging kambing bakar.
Berkali –kali aku melihat suaminya. Lepas tengok suami dia, aku merenung wajahnya.
“Nama?” tanya aku pendek. “Panggil Milah,” jawabnya juga pendek.
“Mesti kak hairan dan tak percaya, kan? Apabila saya tunjukkan siapa suami saya. Sudahlah Pakistan, berumur pula,” katanya sambil ketawa.
Aku tersenyum malu. Pandai pula si Milah membaca isi hati aku. Tiba-tiba muka aku merah.
“Sudah lama kahwin?” soal aku lagi.
“Sudah tujuh tahun, kak. Itu anak lelaki saya. Kacak tak?” jelas Milah.
Aku menoleh ke arah budak lelaki yang ditunjukkan.
“Patutlah kahwin dengan Pakistan sebab hendak anak lawa,” kataku sambil ketawa mengusik.
“Kakak tahu kenapa saya pilih lelaki Pakistan, bukan lelaki Melayu?” soal Milah.
“Kenapa?” tanya aku.
Tersentak aku bila Milah memberikan penjelasan yang panjang lebar. Milah berasal dari daerah Bukit Merah dan berada di kampung yang agak jauh dari bandar.
Suaminya masuk ke kampung Milah dengan menaiki basikal sambil membawa beberapa helai kain batik, pelikat, baju Melayu dan beberapa barangan perempuan.
Ali, sangat peramah dan sangat mesra. Tak pernah berkira sekiranya pelanggan tidak boleh membayar hutang mengikut perjanjian yang telah ditetapkan.
Tidak lama kemudian, Ali tidak lagi masuk ke kampung dengan berbasikal, tetapi bertukar kepada motosikal. Kemudian, bertukar kepada kereta berjenama Proton Saga. Milah pula, tak pernah barangan Ali tidak dibelinya malahan Milah menjadi perantara untuk mengutip hutang daripada pelanggan Ali.
Adakalanya, Milah turut mempromosi barangan jualan Ali kepada pelanggan lain. Lama-kelamaan, cinta berputik dan Milah sanggup menjadi isteri Ali yang sah. Milah tidak kisah pun kalau Ali sudah pun mempunyai isteri di Pakistan. Semasa mereka berkahwin, Milah baharu berusia 18 tahun dan Ali sudah pun berumur 48 tahun.
“Patutlah, aku nampak Ali kelihatan tua,” bisik hatiku. Tanpa aku sedari nasi Arab ku tambah sepinggan lagi sambil mendengar cerita Milah.
Milah dengan bangga berkata, buat apa kahwin dengan lelaki Melayu yang pemalas, kaki main daun terup, suka tunggu kedai kopi, kedekut dan ramai yang kaki dadah.
Milah membilang satu-satu perangai lelaki Melayu yang negatif. Aku berhenti mengunyah nasi.
“Betul juga kata si Milah ni,” bisik hati kecilku.
Aku memandang Milah sambil tersenyum. “Milah tak takut kena tinggal? Nanti dia balik Pakistan, Milah jadi janda,” aku bertanya dengan berhati-hati. Risau juga takut Milah tiba-tiba naik angin.
“Tak takut kak, semua itu takdir Allah. Saya dah bersedia, suami saya sudah ada sebuah kedai runcit di kampung saya. Saya uruskan kedai. Kalau dia tinggalkan saya, Insya-Allah saya dan anak saya tidak merempat. Lagi pun saya masih muda lagi,” panjang lebar Milah menjawab soalan aku.
Aku cuba memancing Milah lagi. Kali ini soalan aku agak mencabar.
“Milah, orang cakap kalau kahwin dengan lelaki Pakistan, cemburunya lain macam sikit. Silap hari bulan awak kena kurung dan kena pukul,” usik aku.
“Sama saja kak, suami Melayu pun kalau yang jenis panas baran, kena pukul juga,” balas Milah sambil tersenyum kelat.
Aku terdiam. Lelaki Melayu sudah hilang permintaan. Kali ini aku pula tersenyum kelat.
Kami sama-sama menghabiskan nasi Arab dan menjamah puding nasi manis ataupun Kheer. Berselera sungguh Milah makan.
Agaknya tekak Milah sudah sebati dengan makanan dari Pakistan. Milah meneruskan hujahnya tentang lelaki Melayu dan Pakistan.
Lelaki Melayu pada pandangan Milah tidak layak dijadikan suami kerana ramai wanita di kampungnya yang merana dan menjadi janda kerana sebab-sebab yang telah dinyatakan.
“Saya bahagia kak, semua keperluan saya disediakan. Nafkah tak terabai. Anak dan keluarga saya dijaga dengan baik. Kami diberikan didikan agama yang sempurna. Kak, sudah kahwin?” tanya Milah sambil meneguk air.
“Kalau belum kahwin, saya boleh tolong carikan lelaki Pakistan untuk kakak,” pelawa Milah.
Hampir tersembur air yang kuminum.
“Tak apalah Milah, kak tetap memilih lelaki Melayu sebagai pasangan, lagipun kak sudah berkahwin,” sambil ketawa aku menjawab. Milah mengangguk mendengar jawapan aku.
Setelah selesai makan, aku minta izin untuk berundur. Sepanjang perjalanan pulang, sambil memandu Exora, aku mencari satu kesimpulan pada kisah Milah. Rasa tersepit antara realiti yang perlu aku akur pada ruang yang menyakitkan.
Sudah berapa ramai perempuan Melayu menjanda apabila ditinggalkan suami berbangsa asing. Terkontang-kanting sendirian menguruskan anak-anak. Milah mungkin di antara yang bertuah.
Tiba-tiba aku teringat gula di dapur sudah habis. Terpandang logo Kedai Laila di seberang jalan. Aku terus membelokkan kereta. Tanpa berlengah aku menuju ke dalam kedai dan mengambil sekilo gula dan sebungkus biskut. Menuju ke kaunter bayaran aku terpandang seorang wanita yang sudah agak berusia sedang melayan urusan belian pelanggan.
“Abang, berapa harga sekilo gandum cap Faiza ni,” laungnya sambil mengangkat gandum tersebut.
Aku berpaling ke belakang dan sekali lagi dadaku berdegup kencang.
Seorang jejaka bermata biru, hidung mancung dengan rambut kemerah-merahan berjalan menuju ke arah kaunter. Shah Rukh Khan? Salman Khan? Pakistan lagi?
Aku meletakkan barang yang dibeli di kaunter. “Kedai awak ke ni?” tanya aku spontan. “Ya, kedai saya. Itu suami saya,” jelas wanita tersebut. Mungkin dia faham apa yang sedang aku fikirkan.
Aku tersenyum lesu sambil mengangguk. Selesai urusan bayaran , aku terus ke kereta. Hebat sungguh penangan jejaka berhidung mancung dan bermata biru ini. Perempuan Melayu yang hilang punca atau lelaki Pakistan yang mengambil kesempatan? Bukan sahaja berkahwin dengan wanita tempatan tetapi turut merampas ekonomi orang tempatan.
“Ah, kasihan dengan lelaki Melayu. ‘Tak Akan Melayu Hilang di Dunia’ sudah tidak boleh diagungkan lagi. Lelaki Melayu sudah layu di tangan lelaki Pakistan, Bangladesh dan Nepal,” keluh aku sambil memaut stereng kereta.
Aku terus memandu sambil melayan lagu Hindustan.